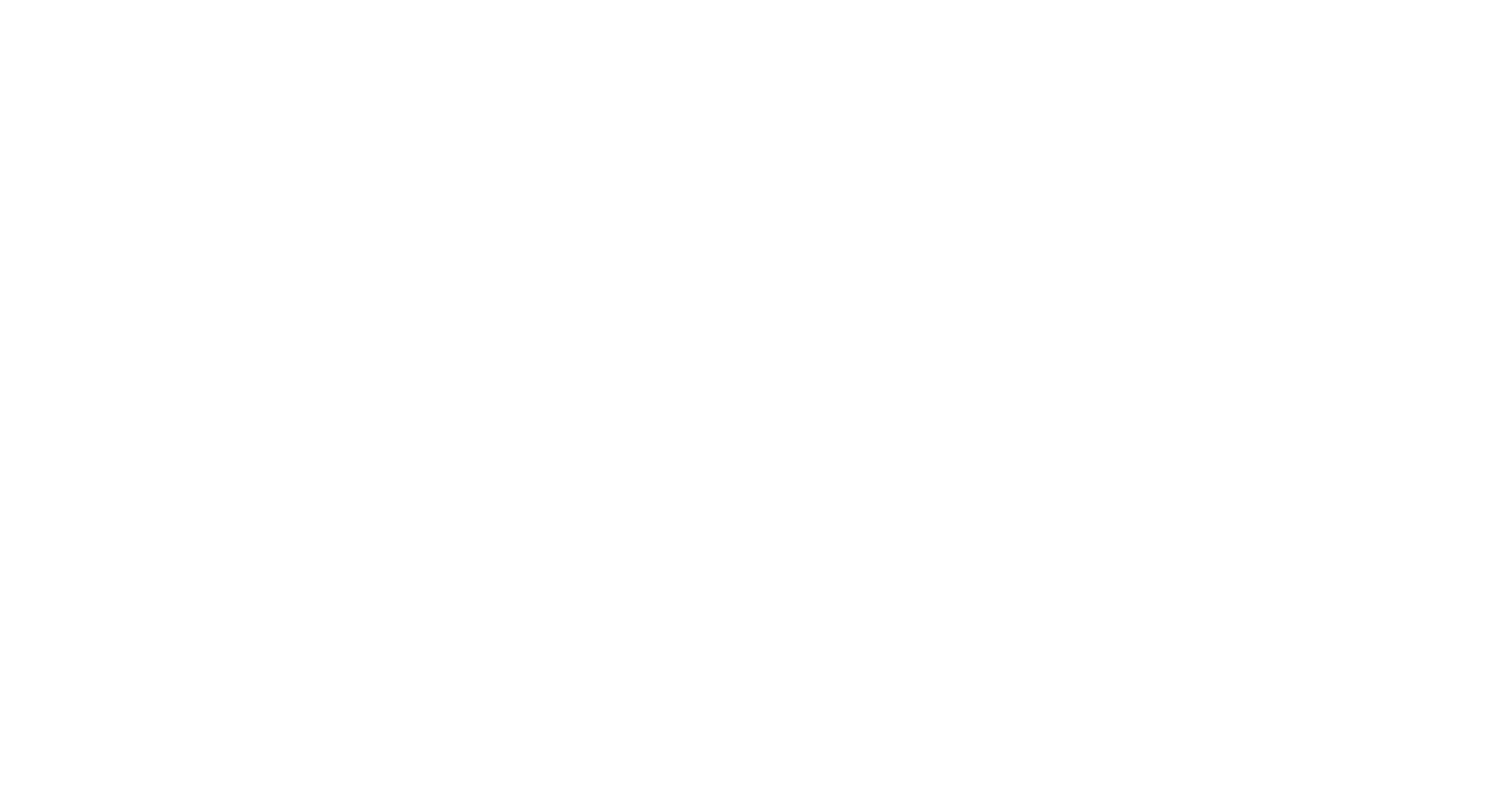Jakarta, The PRAKARSA – Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) ke UNFCCC pada 27 Oktober 2025. Dokumen SNDC ini tidak lagi menggunakan skenario CM1 dan CM2 seperti ENDC sebelumnya, namun dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), terdiri atas LCCP-L dan LCCP-H. Target juga beralih dari target berbasis persentase menjadi tingkat absolut emisi GRK tahun 2035 dengan acuan tahun referensi 2019. Terdapat tiga skenario digunakan dalam proyeksi emisi, yaitu CPOS (Current Policy Scenario) atau CM1 dari ENDC, serta LCCP yang sejalan dengan target 1,5°C Paris Agreement. Dua skenario LCCP_L dan LCCP_H memperoyeksikan tingkat emisi absolut lebih rendah 8 dan 17,5% secara berurutan dibandingkan skenario CM2 ENDC.
Meskipun Pemerintah menegaskan SNDC sebagai wujud kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim global, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Peneliti The PRAKARSA, Yuanda Pangi Harahap, menilai penyusunan dokumen SNDC mengalami kemunduran komitmen “Sebagai contoh, perubahan target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang menurun menjadi menjadi 17-19% pada 2025, dari target sebelumnya yang menargetkan sebesar 23% pada 2025. Padahal, kita tahu bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar (55%). Ini jelas bertentangan dengan proyeksi skenario LCCP yang menargetkan tingkat emisi absolut lebih rendah dibandingkan skenario CM2 ENDC.”
Yuanda menambahkan penyusunan dokumen ini juga minim partisipasi dari organisasi masyarakat sipil. “Partisipasi publik dalam forum konsultasi hanya sebatas menerima sosialisasi dokumen, tanpa kesempatan untuk memberikan masukan substansial karena terbatasnya waktu sebelum dokumen diserahkan ke UNFCCC. Hal ini melemahkan ambisi dan implementasi nyata terhadap komitmen terhadap iklim yang inklusif dan transparan.”
Di sisi lain, Yuanda menyorot terkait tata kelola baik yang tertuang dalam dokumen SNDC maupun implementasi first NDC sebelumnya. “Sejak komitmen awal Indonesia pada 2016 melalui first NDC, Updated NDC 2021, dan Enhanced NDC 2022, distribusi target penurunan emisi ke pemerintah daerah belum diinternalisasi dengan baik, padahal peran daerah sangat penting dalam operasionalisasi industri, sektor pengelolaan limbah, dan sektor transportasi yang berada di bawah kewenangan mereka.”
Sejalan dengan hal tersebut, Yuanda menyampaikan bahwa sistem monitoring dan evaluasi saat ini menciptakan kebingungan karena belum terintegrasi. Ia menjelaskan, “Saat ini, pelaporan emisi dari pemerintah daerah dilakukan melalui platform SIGN-SMART yang dikelola oleh KLHK, sementara Bappenas juga memiliki platform AKSARA yang tidak hanya memuat data emisi, tetapi juga dilengkapi dengan Rencana Aksi Daerah. Sayangnya, data yang ditampilkan pada kedua platform tersebut belum selaras, sehingga menimbulkan kebingungan publik dalam mencari informasi yang akurat dan dapat diandalkan.”
Komitmen penurunan emisi membutuhkan ketersediaan pendanaan. KLH memproyeksikan kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 4.520 Triliun untuk periode 2018–2030 dan sebesar Rp. 7.551 Triliun untuk periode 2031–2035. Peneliti Sustainable Finance The PRAKARSA, Dwi Rahayu Ningrum menegaskan bahwa mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk mendukung aksi iklim. “Potensi pembiayaan privat ini sangat besar jika diarahkan ke sektor-sektor hijau yang berorientasi pada dekarbonisasi, efisiensi energi, dan pembangunan rendah karbon. Melalui penerapan sustainable finance melalui green bonds, transition finance, dan blended finance, sektor keuangan dapat menjadi penggerak penting dalam mewujudkan transisi yang adil dan memperkuat ekonomi hijau Indonesia.”
Dwi juga menambahkan pentingnya mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia agar dokumen NDC tidak hanya berakhir pada perencanaan. “Selain memantau progres penurunan emisi, kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas pendanaan yang telah diakses. Misalnya melalui BPDLH sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana untuk pendanaan lingkungan hidup dan iklim di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.” Pendekatan yang transparan, akuntabel, serta pengawasan ketat pada implementasi sangat diperlukan agar dana dapat dimanfaatkan secara efektif dan membuka peluang mengakses pendanaan lain untuk mendukung target iklim nasional.
a mengirimkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) ke UNFCCC pada 27 Oktober 2025. Dokumen SNDC ini tidak lagi menggunakan skenario CM1 dan CM2 seperti ENDC sebelumnya, namun dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), terdiri atas LCCP-L dan LCCP-H. Target juga beralih dari target berbasis persentase menjadi tingkat absolut emisi GRK tahun 2035 dengan acuan tahun referensi 2019. Terdapat tiga skenario digunakan dalam proyeksi emisi, yaitu CPOS (Current Policy Scenario) atau CM1 dari ENDC, serta LCCP yang sejalan dengan target 1,5°C Paris Agreement. Dua skenario LCCP_L dan LCCP_H memperoyeksikan tingkat emisi absolut lebih rendah 8 dan 17,5% secara berurutan dibandingkan skenario CM2 ENDC.
Meskipun Pemerintah menegaskan SNDC sebagai wujud kesungguhan dan komitmen Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim global, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Peneliti The PRAKARSA, Yuanda Pangi Harahap, menilai penyusunan dokumen SNDC mengalami kemunduran komitmen “Sebagai contoh, perubahan target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang menurun menjadi menjadi 17-19% pada 2025, dari target sebelumnya yang menargetkan sebesar 23% pada 2025. Padahal, kita tahu bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar (55%). Ini jelas bertentangan dengan proyeksi skenario LCCP yang menargetkan tingkat emisi absolut lebih rendah dibandingkan skenario CM2 ENDC.”
Yuanda menambahkan penyusunan dokumen ini juga minim partisipasi dari organisasi masyarakat sipil. “Partisipasi publik dalam forum konsultasi hanya sebatas menerima sosialisasi dokumen, tanpa kesempatan untuk memberikan masukan substansial karena terbatasnya waktu sebelum dokumen diserahkan ke UNFCCC. Hal ini melemahkan ambisi dan implementasi nyata terhadap komitmen terhadap iklim yang inklusif dan transparan.”
Di sisi lain, Yuanda menyorot terkait tata kelola baik yang tertuang dalam dokumen SNDC maupun implementasi first NDC sebelumnya. “Sejak komitmen awal Indonesia pada 2016 melalui first NDC, Updated NDC 2021, dan Enhanced NDC 2022, distribusi target penurunan emisi ke pemerintah daerah belum diinternalisasi dengan baik, padahal peran daerah sangat penting dalam operasionalisasi industri, sektor pengelolaan limbah, dan sektor transportasi yang berada di bawah kewenangan mereka.”
Sejalan dengan hal tersebut, Yuanda menyampaikan bahwa sistem monitoring dan evaluasi saat ini menciptakan kebingungan karena belum terintegrasi. Ia menjelaskan, “Saat ini, pelaporan emisi dari pemerintah daerah dilakukan melalui platform SIGN-SMART yang dikelola oleh KLHK, sementara Bappenas juga memiliki platform AKSARA yang tidak hanya memuat data emisi, tetapi juga dilengkapi dengan Rencana Aksi Daerah. Sayangnya, data yang ditampilkan pada kedua platform tersebut belum selaras, sehingga menimbulkan kebingungan publik dalam mencari informasi yang akurat dan dapat diandalkan.”
Komitmen penurunan emisi membutuhkan ketersediaan pendanaan. KLH memproyeksikan kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 4.520 Triliun untuk periode 2018–2030 dan sebesar Rp. 7.551 Triliun untuk periode 2031–2035. Peneliti Sustainable Finance The PRAKARSA, Dwi Rahayu Ningrum menegaskan bahwa mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk mendukung aksi iklim. “Potensi pembiayaan privat ini sangat besar jika diarahkan ke sektor-sektor hijau yang berorientasi pada dekarbonisasi, efisiensi energi, dan pembangunan rendah karbon. Melalui penerapan sustainable finance melalui green bonds, transition finance, dan blended finance, sektor keuangan dapat menjadi penggerak penting dalam mewujudkan transisi yang adil dan memperkuat ekonomi hijau Indonesia.”
Dwi juga menambahkan pentingnya mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia agar dokumen NDC tidak hanya berakhir pada perencanaan. “Selain memantau progres penurunan emisi, kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas pendanaan yang telah diakses. Misalnya melalui BPDLH sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana untuk pendanaan lingkungan hidup dan iklim di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.” Pendekatan yang transparan, akuntabel, serta pengawasan ketat pada implementasi sangat diperlukan agar dana dapat dimanfaatkan secara efektif dan membuka peluang mengakses pendanaan lain untuk mendukung target iklim nasional.