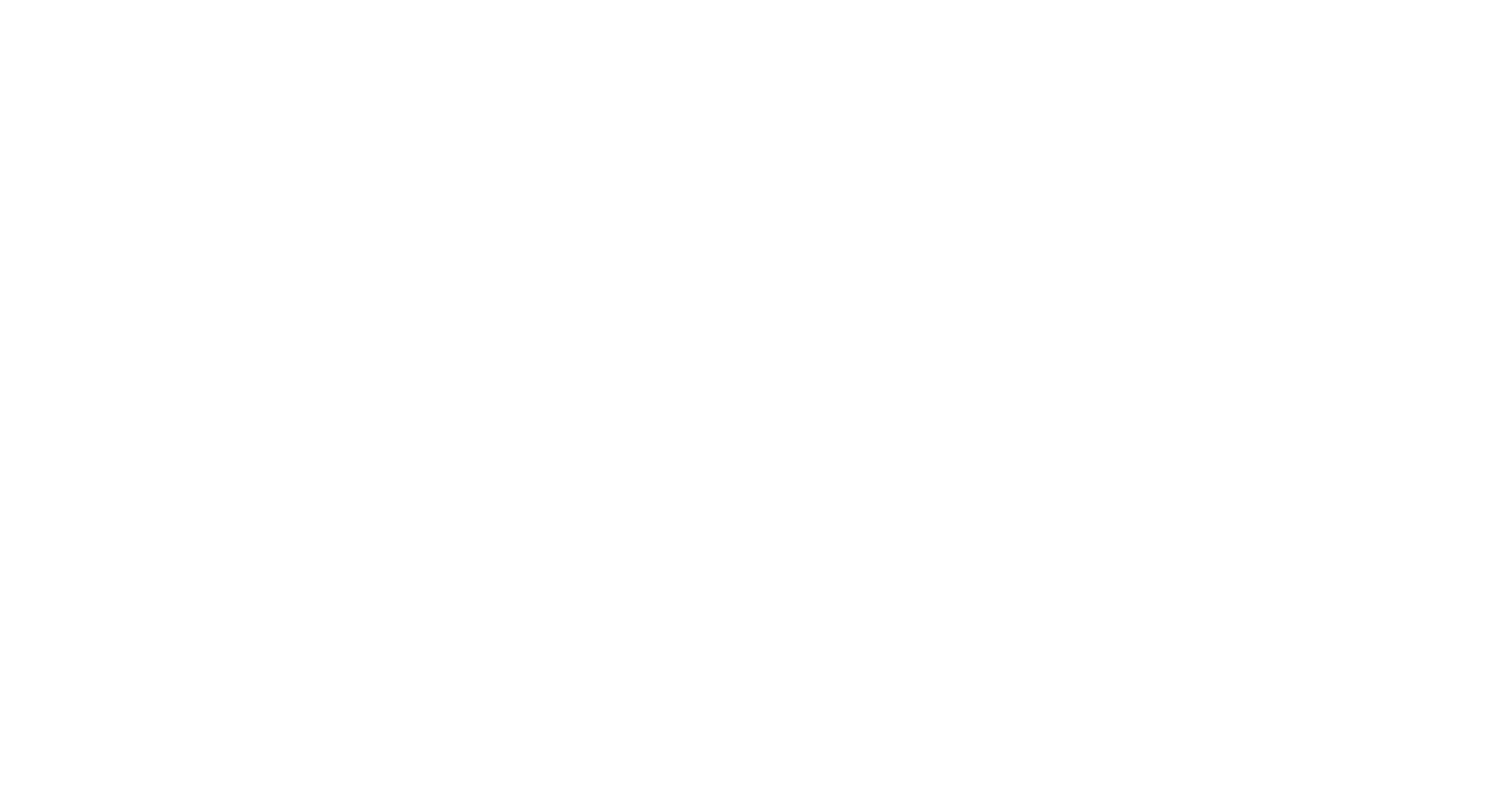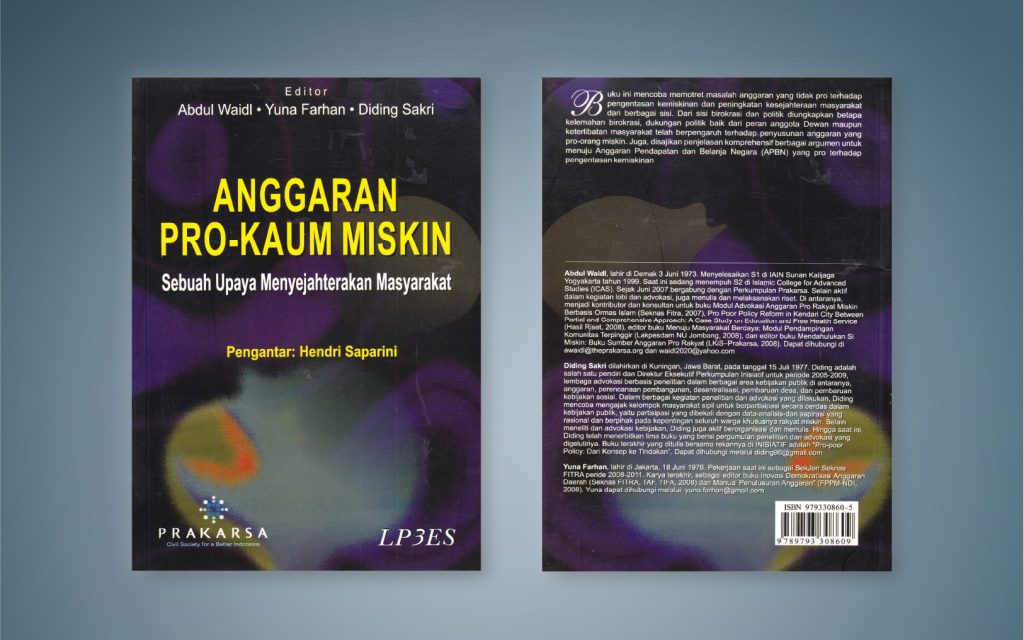
Abdul Waidl, Yuna Farhan, Diding Sakri (editor)
ISBN 978-979-3330-86-0
Pengantar : Hendri Saparini
Penerbit Pustaka LP3ES dan Perkumpulan PRAKARSA
Cetakan Pertama, Desember 2009
xxvi + 339 hlm ; 15,5 x 23 cm
Tayangan di televisi tentang bapak dan ibu muda yang menjadikan gerobak dorongnya sebagai alat mencari nafkah sekaligus rumah tempat membesarkan anak-anak mereka, juga cerita orang tua yang terpaksa membiarkan anak-anaknya ikut mencari nafkah karena tidak mampu menyekolahkan mereka, semakin sering kita saksikan. Belum lagi berita meningkatnya jumlah penderita gizi buruk dan masyarakat miskin yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih atau pelayanan umum lainnya, seolah tidak pernah habis. Tentu kita sepakat bahwa pemberitaan yang marak tentang berbagai masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat miskin bukan sekadar buah dari kebebasan pers, tetapi jumlah orang miskin memang masih sangat banyak.
Sangat ironis setelah Indonesia melakukan pembangunan selama lebih dari 63 dan telah menguras berbagai sumber daya alam, ternyata menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin dalam. Sekelompok kecil masyarakat telah hidup dengan sangat berkecukupan, mampu mendapatkan pendidikan terbaik, fasilitas kesehatan yang sangat berkualitas, pekerjaan yang sangat layak, tinggal di lingkungan mewah dengan fasilitas publik nomor satu, dll; namun di lain pihak masih ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang tingkat kesejahteraannya masih jauh tertinggal. Jangankan mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pelayanan fasilitas publik yang layak, untuk sekadar makan, pakaian dan tempat tinggal layak pun banyak masyarakat yang tidak dapat mendapatkannya.
Salah satu buktinya, dalam APBN 2008 dianggarkan sebanyak 19,2 juta keluarga Indonesia layak menerima Raskin (beras untuk keluarga miskin), artinya ada sekitar 50 juta orang yang masih memerlukan bantuan beras. Dalam pelaksanaannya ternyata, jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding yang dianggarkan sehingga jatah beras sebesar 10 kg per keluarga per bulan harus dikurangi agar bisa dibagi lebih merata. Selain berbagai kelemahan dalam administrasi, meningkatnya jumlah keluarga miskin adalah akibat beban masyarakat kelompok bawah yang semakin berat. Buruk dan terbatasnya pelayanan kebutuhan dasar yang semestinya menjadi pelayanan publik, saat ini harus ditanggung masyarakat seperti biaya pendidikan, transportasi, kesehatan, dll.
Peran Pemerintah Lewat APBN
Salah satu senjata ampuh yang dimiliki negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adalah lewat kebijakan anggaran yang mengatur sumber penerimaan dan kebijakan pengeluaran pemerintah. Penyusunan rencana, pelaksanaan serta pengawasan anggaran yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan DPR seharusnya akan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat ampuh menuju pembangunan yang lebih adil. Artinya Semakin besar APBN semakin merata pembangunan untuk seluruh rakyat.
Apalagi Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pada negara untuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan ini telah dengan tegas dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945 baik yang asli maupun hasil amandemennya. Pasal 23 ayat 1 misalnya dengan jelas ditegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masih banyak pasal dalam konstitusi yang mengatur dengan jelas hak rakyat dan tugas negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat; tentang pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam sebesar-besar kemakmuran rakyat; amanah bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll.
Konstitusi telah mengatur apa yang menjadi hak rakyat dari berbagai penerimaan negara yang dikelola negara dan dengan tegas menentukan kewajiban-kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak rakyat dari pengelolaan APBN. Semestinya semakin besar volume anggaran pemerintah semakin besar pula kapitas pemerintah untuk melaksanakan amanah konstitusi untuk membawa rakyat lebih sejahtera, namun yang terjadi tidak demikian.
Sebagai ilustrasi, APBN meningkat pesat dari Rp 380 triliun (2004) menjadi sekitar Rp 980 triliun (2008). Namun, hasil pembangunan yang diperoleh selama periode tersebut tidak sebanding. Untuk pengentasan kemiskinan, misalnya, meskipun anggaran kemiskinan meningkat tajam dari Rp 18 triliun (2004) menjadi sekitar Rp 70 triliun (2008), akan tetapi jumlah orang miskin tidak berkurang secara signifikan. Bila para tahun 2004 jumlah orang miskin sebanyak 36 juta orang maka pada tahun 2008 tetap sebesar 35 juta orang. Bahkan jumlah orang miskin kemungkinan akan lebih besar bila survei dilakukan setelah kenaikan harga BBM bulan Mei 2008.
Peran Lewat Pro Poor Policy
Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kebijakan makroekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat atau pro-poor macroeconomic policy. Tentu saja kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh/komprehensif baik pada kebijakan fiskal dan moneter maupun industri dan perdagangan.
Kebijakan fiskal. Bila program penghapusan kemiskinan dan pengagguran menjadi prioritas pembangunan, maka sebagai konsekwensinya pemerintah dituntut untuk memiliki kebijakan fiskal yang pro-penghapusan kemiskinan (pro-poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job). Dalam penyusunan penerimaan negara misalnya, cara-cara untuk meningkatkan penerimaan seharusnya tidak kontra produktif terhadap upaya penghapusan kemiskinan. Penghematan anggaran dengan pencabutan subsidi rakyat seharusnya menjadi pilihan paling akhir setelah pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan lain.
Demikian pula upaya meningkatan penerimaan dari sumber pajak, semestinya dihindarkan dari pilihan kebijakan yang akan berdampak langsung bagi kelompok rakyat miskin. Pertumbuhan pajak langsung (direct tax) seperti PPh harus diutamakan dibanding pajak-pajak tidak langsung (indirect tax) seperti pajak penjualan, dll karena akan berdampak langsung bagi rakyat miskin. Reformasi kebijakan juga harus dilakukan terhadap penerimaan pemerintah dari pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang, seperti: renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan yang selama ini hanya memberikan manfaat minimal bagi rakyat atau langkah sekuritisasi sumber migas harus menjadi alternatif prioritas.
Di sisi belanja, kebijakan alokasi belanja semestinya diprioritaskan pada pengeluaran-pengeluaran yang akan memberikan dampak positif (multiplier effect) bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Pengajuan penghapusan utang atau pembatasan utang harus menjadi langkah strategi yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengurangi beban APBN. Namun, berbagai alternatif tersebut tidak akan pernah muncul apabila paradigma neoliberal yang mendasari pengelolaan anggaran. Stimulus ekonomi yang memerlukan dukungan anggaran pembangunan besar, misalnya, sangat sulit dilakukan karena langkah ini bertentangan dengan konsep paradigma yang konservatif. Anggaran belanja justru diupayakan amat ketat. Upaya mencari pembiayaan dengan penghapusan utang, pembatasan penggunaan anggaran untuk pembayaran cicilan utang, melakukan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan atau sekuritisasi migas, juga tidak akan menjadi pilihan karena bertentangan dengan paradigma yang dianut.
Kebijakan moneter. Sebagaimana pengelolaan kebijakan fiskal, kebijakan moneter pun harus pro terhadap penyelesaian kemiskinan dan pengangguran. Kegagalan dalam mengelola kebijakan makro, seperti dalam pengendalian harga, juga menjadi penyebab turunnya kesejahteraan masyarakat. Tahun 2007-2008, tingkat inflasi bahan makanan sebesar 11,3 dan 13,5 persen jauh lebih tinggi dibanding inflasi umum yang sebesar 6,6 persen dan 9,4 persen. Dengan gambaran beban inflasi makanan saja dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat bawah akan terpangkas oleh inflasi. Sebagaimana diketahui 70 persen pengeluaran kelompok miskin maupun mendekati miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Apalagi bila diperhitungkan hasil survei BPS dan ADB yang menyimpulkan bahwa inflasi yang dihadapi orang miskin 2-3 kali lipat dari rata-rata nasional. Semakin tegas bahwa kesejahteraan masyarakat bawah akan terus merosot dan gap akan semakin tajam tanpa perombakan kebijakan dan peran pemerintah.
Pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui kebijakan moneter maupun kebijakan sektor riil. Permasalahan inflasi di Indonesia lebih banyak diakibatkan oleh permasalahan di sektor riil, akan tetapi, dengan paradigma ekonomi yang konservatif dan monetaris (fokus pada pilihan kebijakan-kebijakan moneter), inflasi lebih sering diredam dengan kebijakan moneter. Kesalahan pilihan kebijakan ini jelas kontra produktif terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat suku bunga tinggi berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan biaya produksi. Tekanan ganda (double pressure) inilah yang akhirnya mendorong PHK besar. Kalaupun pemerintah melakukan langkah kebijakan di sektor riil akan tetapi fokus utamanya lebih diarahkan pada penyelamatan moneter. Sehingga seringkali mengabaikan dampak negatifnya terhadap sektor riil.
Kebijakan perdagangan dan industri. Prioritas kebijakan sektoral sangat menentukan kualitas pertumbuhan dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih disokong oleh pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi padat modal dan teknologi tinggi. Orientasi kebijakan yang lebih memprioritaskan sektor spekulatif akhirnya mengurangi pertumbuhan pada sektor riil. Akibatnya, daya serap tenaga kerja yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi semakin rendah.
Sebagai gambaran, dalam RPJM 2005-2009 target penciptaan lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi adalah 450.000 tenaga kerja. Namun data Sakernas 2005-2006 mencatat jumlah lapangan kerja neto yang bisa disediakan per 1 persen pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika sebelum tahun 2004 daya serap neto 1 persen pertumbuhan dapat mencapai 240.000-250.000 lapangan kerja dan tahun 2004 menurun hingga di bawah 200.000, maka tahun 2005-2006 daya serap dari pertumbuhan ekonomi hanya berkisar antara40.000-50.00040.000-50.000 lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan. Penurunan kualitas pertumbuhan terjadi karena pertumbuhan ekonomi saat ini bukan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi di sektor-sektor padat karya seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan tetapi sektor keuangan dan telekomunikasi yang sangat padat modal.
Pilihan kebijakan liberalisasi pertanian yang tanpa persiapan juga mengakibatkan menurunnya kesejahteraan petani. Kondisi ini sangat berbeda dengan negara-negara tetap meyakini pentingnya peran pemerintah yang luas. Negara-negara Eropa atau Jepang menempatkan strategi pengembangan sektor pertanian dengan melakukan berbagai langkah penyelamatan dari gelombang liberalisasi. Memang saat ini sangat sulit untuk melakukan kebijakan perang tarif (tariff barrier). Akan tetapi masih sangat banyak kebijakan lain untuk mendukung sektor pertanian. Sebagai contoh, peran pemerintah yang besar ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah yang besar untuk mendukung daya saing produk para petani.
Kebijakan liberalisasi perdagangan yang gencar dilakukan semakin menekan daya saing produk lokal di pasar domestik melalui membanjirnya produk impor legal maupun ilegal. Liberalisasi sektor perdagangan dan industri juga berdampak buruh pada pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Di sektor garmen, saat ini 77 persen pasar garmen dometik dikuasai produk impor dengan 70 persen nya adalah produk illegal. Keputusan untuk mengekspor rotan mentah misalnya, berdampak besar pada kebangkrutan industri mebel rotan di Cirebon dan Sidoarjo yang akhirnya mendorong gelombang PHK.
Konsistensi PRAKARSA
Selama ini ‘Perkumpulan PRAKARSA’ selalu konsisten dalam mendukung perwujudan APBN yang pro-poor, yang hingga saat ini masih belum juga terwujud. Keresahan tersebut akhirnya dituangkan dengan sangat baik dalam buku ini. Studi ini mencoba memotret masalah anggaran yang tidak pro terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi. Dari sisi birokrasi dan politik diungkapkan betapa kelemahan birokrasi, dukungan politik baik dari peran anggota Dewan maupun keterlibatan masyarakat telah berpengaruh terhadap penyusunan anggaran yang pro orang miskin.
Dalam buku ini disajikan penjelasan dengan sangat komprehensif berbagai argumen untuk menuju APBN yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam strategi alokasi anggaran, argumen bahwa anggaran yang pro-poor harus terkait dengan pembangunan social sector jangka panjang, sangat menarik. Selama ini seolah ada keterpisahan. Bahkan dengan kecenderungan pemerintah akan mengalihkan tanggung jawab pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat lewat berbagai program mandiri seperti PNPM Mandiri. Dengan dana PNPM Mandiri masyarakat boleh memanfaatkannya untuk pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, pendidikan, pembangunan jalan, dll. Dana yang sangat besar (tahun 2007 akan mencapai Rp 77 triliun) semestinya tidak digunakan untuk program-program jangka pendek. Penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terpusat sehingga lebih efektif dan akan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi jangka panjang.
Pembahasan penting lainnya adalah tentang anggaran pro-poor yang harus direncanakan secara benar tidak hanya dalam pemilihan prioritas program alokasinya tetapi juga dalam pilihan strategi pembiayaan pembangunan. Saat ini perhatian masyarakat termasuk juga para anggota Dewan lebih terkonsentrasi pada strategi alokasi bukan pada pembiayaan. Padahal seperti disampaikan dalam buku ini, strategi pembiayaan yang salah akan menimbulkan beban bagi masyarakat di masa mendatang. Pembahasan tentang pajak dan alternatif pembiayaan sangat penting. Ternyata ada alternatif pembiayaan yang lebih adil dan terfokus sehingga menjamin bahwa pembiayaan tersebut benar-benar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Terakhir, kami mengucapkan selamat pada para penulis yang telah menyajikan informasi yang sangat bermanfaat. Buku ini akan sangat bermanfaat untuk anggota DPR, Pemerintah maupun masyarakat luas karena mampu penjelaskan dan memberikan argumen dengan luas tentang pentingnya bagi Indonesia untuk segera mewujudkan anggaran pro-poor untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang semakin dalam.
Bagian Satu:
Menyorot Problem Kunci Mendorong Anggaran Pro Kaum Miskin di Indonesia
————————–
- Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik
- Kebijakan Fiskal Setelah Krisis Menilai dari Perspektif Anggaran Pro Kaum Miskin
- Transmisi Moneter Tanpa Pengemudi Fiskal
- Peran Parlemen dalam Sistem Penganggaran di Berbagai Negara:
- Politik Birokrasi Anggaran di Indonesia
- Studi Pemetaan Persepsi Mengenai Anggaran Pro Kaum Miskin di Indonesia
Bagian Dua:
Menjajaki Solusi Tercapainya Anggaran Pro Kaum Miskin di Indonesia
————————–
- Optimalisasi Penerimaan Negara untuk Pembiayaan Pembangunan Nasional
- ORI Terfokus: Stimulus Fiskal ke Arah Bekerja Penuhnya Sistem Ekonomi
- Belanja Pendidikan dan Kesehatan yang Lebih Signifikan
- Menciptakan DPR dan Sistem Pendukung Parlemen yang Mendukung Anggaran Pro Kaum Miskin
- Strategi CSO Working Group dan Penguatan Panitia Anggaran