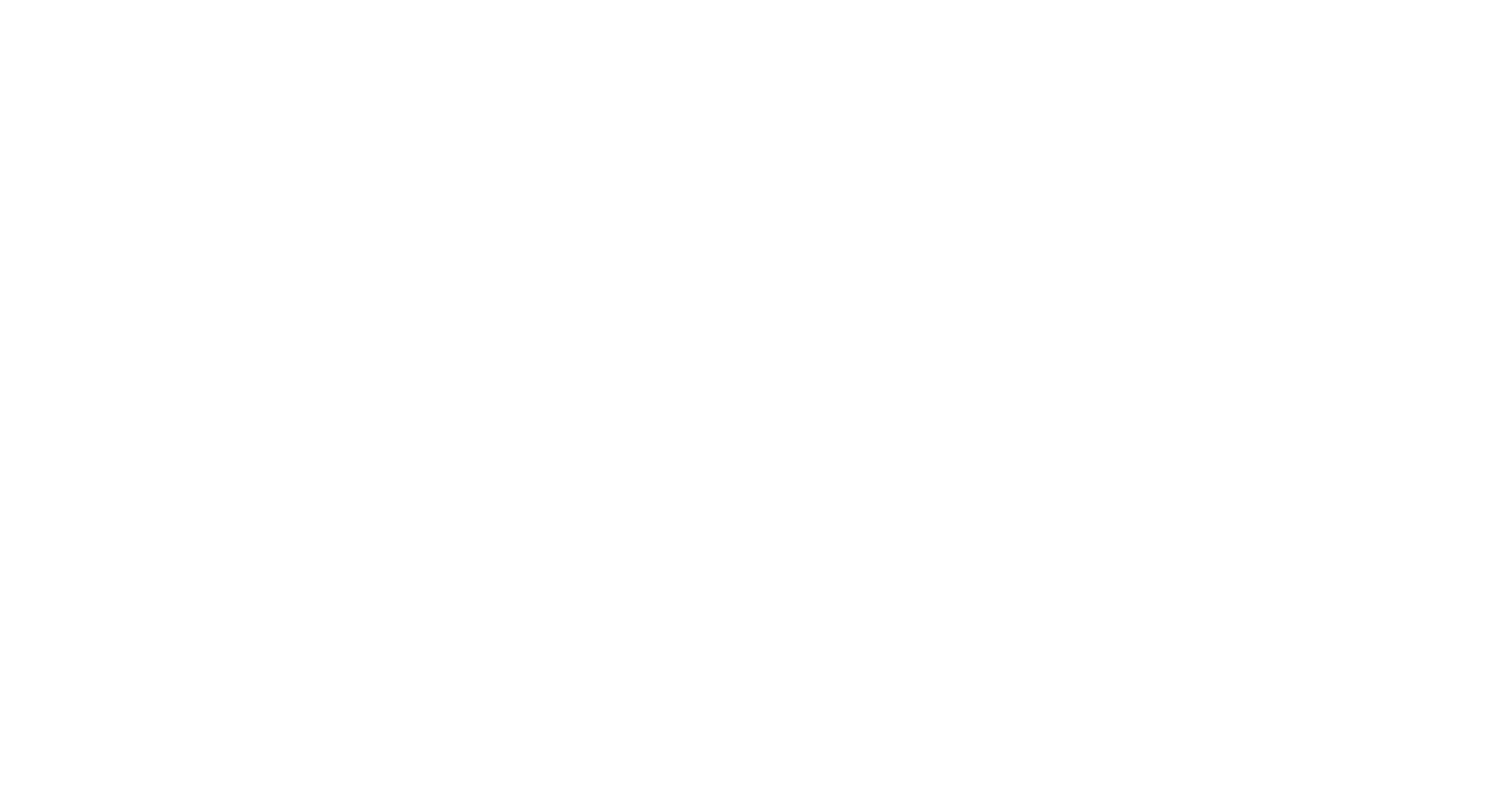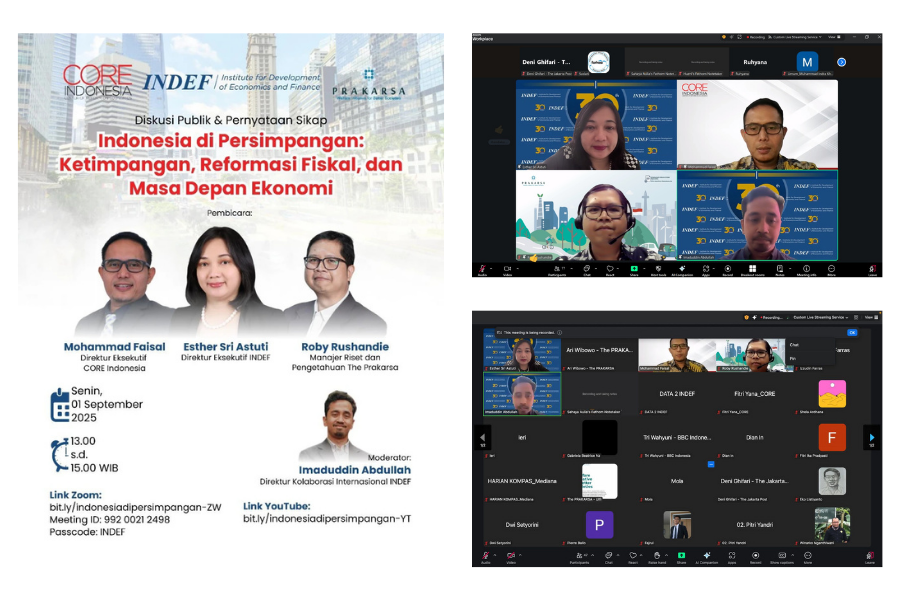
Jakarta, 1 September 2025 – The PRAKARSA, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebagai lembaga think tank ekonomi dan kebijakan publik mencermati dengan serius perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dalam beberapa hari terakhir, dan menilai bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi mencerminkan kegagalan fundamental dalam pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.
Mohammad Faisal – Direktur Eksekutif CORE Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi demonstrasi yang berujung pada kekacauan, yang berakar pada akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap ketidakadilan ekonomi, yang tercermin dari lebarnya ketimpangan antara kaya dan miskin, masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, menurunnya daya beli kelas menengah bawah dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
“Meskipun jumlah penduduk miskin cenderung menurun, berdasarkan data terakhir dari BPS per Maret 2025 jumlahnya masih mencapai 24 juta orang. Namun, jika kita melihat masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan, dengan ambang pengeluaran per kapita di bawah Rp1 juta per bulan, jumlahnya tidak kurang dari 100 juta orang. Itu setara dengan lebih dari sepertiga total penduduk Indonesia,” jelas Faisal.
Selain itu, Faisal menambahkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memang menurun, tetapi persentase pekerja informal mendekati 60 persen . Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur juga meningkat signifikan. Di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) melonjak tajam. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari–Juli 2025 terdapat 43.500 kasus PHK, atau meningkat 1,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Jumlah kasus PHK tahun ini bahkan jauh lebih tinggi lagi jika mengacu pada catatan APINDO.
Menanggapi kondisi ini, Faisal menekankan perlunya respons cepat dari pemerintah dan elit politik melalui langkah korektif yang nyata. Di antaranya: membatalkan kebijakan pajak yang membebani masyarakat; merevisi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu pungutan pajak lokal berlebihan; serta menghentikan belanja yang tidak produktif, seperti pembentukan lembaga baru, pemberian insentif berlebih, dan pembiayaan pinjaman rumah bagi anggota DPR.
Sebaliknya, anggaran negara harus difokuskan pada penciptaan lapangan kerja masif di sektor padat karya, program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi (bukan sekadar bantuan sosial yang rawan politisasi), serta langkah antisipatif terhadap tekanan eksternal, misalnya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang berpotensi memperburuk impor dan melemahkan sektor domestik.
Di akhir pernyataannya, Faisal menegaskan bahwa ia menghargai demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia mengajak masyarakat untuk menghindari tindakan penjarahan dan perusakan. Ia juga meminta pemerintah untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif, guna meredakan situasi.
Roby Rushandie – Manajer Riset dan Pengetahuan The PRAKARSA menyoroti krisis pekerjaan layak di Indonesia sebagai akar tragedi demonstrasi terkini. Hal ini ironis mengingat euforia pemerintah atas penurunan angka kemiskinan dan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Meski angka pengangguran turun, sektor informal justru mendominasi dengan 86,58 juta pekerja pada Februari 2025 atau meningkat dari tahun sebelumnya, sementara pekerja formal stagnan dalam 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini ditandai dari pekerja platform seperti ojek online yang meningkat dari 3,62 juta pada 2019 menjadi 4,22 juta pada 2024.
Survei The PRAKARSA terhadap 213 responden mengungkap bahwa 60 persen menganggap ojek online sebagai pekerjaan utama dan 26 persen ojek online bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Selain itu, hanya 12 persen dari 4,6 juta pekerja platform yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, pendapatan rata-rata ojek online yang dikutip dari survei IDEAS, turun dari Rp309.000/hari sebelum pandemi (2018-2019) menjadi Rp175.000/hari (2022-2023).
Penyebab utamanya tingginya pekerja informal yakni deindustrialisasi dini sejak 10 hingga 20 tahun lalu, penurunan sektor manufaktur, dan perlambatan penyerapan tenaga kerja. Situasi ini menyebabkan kerentanan, seperti tergambarkan dalam tragedi Affan Kurniawan. “Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan memperlihatkan bagaimana pekerja informal selama ini yang menjadi penyangga ekonomi di perkotaan, namun tanpa kepastian kerja, upah layak, jaminan sosial, dan juga minim dari perhatian pemerintah” ucap Roby.
Roby merekomendasikan reformasi mendesak untuk perlindungan sosial yang berkeadilan, yakni mengembangkan kerangka pekerjaan layak yang mencakup upah dan jam kerja yang manusiawi serta jaminan keselamatan; membentuk undang-undang tripartit yang mengatur pekerja platform digital; mengintegrasikan 4,6 juta pekerja platform ke dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan kontribusi yang proporsional; menjalankan program padat karya tunai secara masif untuk korban PHK dan pengangguran; serta mempercepat kepastian hukum integrasi standar bisnis, HAM, dan lingkungan untuk menarik investasi berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan Kartu Prakerja yang tidak hanya pelatihan online tetapi juga program magang, pelatihan kerja, dan kontrak kerja yang jelas. Reformasi fiskal juga diperlukan dengan menerapkan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya untuk, menunda kenaikan PBB-P2, serta menghentikan subsidi PPh21 untuk anggota DPR dan pejabat negara. “Pemerintah perlu menerapkan pajak kekayaan kepada kelompok super kaya untuk menjalankan fungsi redistribusi.” tegasnya.
Esther Sri Astuti – Direktur Eksekutif INDEF menyoroti ketidakadilan fiskal sebagai salah satu pemicu utama demonstrasi. “Ini masalah perut. Pajak Bumi dan Bangunan naik drastis, sementara tunjangan DPR justru luar biasa. Rata-rata upah pekerja hanya sekitar Rp5 juta per bulan, sedangkan pendapatan anggota DPR mencapai 20 kali lipatnya,” ungkapnya. Ia juga menekankan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja, maraknya kasus PHK, serta rendahnya upah yang berakibat pada penurunan kelas menengah. Kondisi ini diperparah dengan semakin dominannya sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia.
Kemudian, analisis Esther terhadap tren belanja APBN menunjukkan bahwa perkembangan belanja modal lebih kecil daripada belanja rutin dimana belanja pegawai, belanja barang, dan bunga utang mengalami kenaikan, sedangkan subsidi dan bansos alami penurunan. Pada sisi lain, pendapatan pajak melambat dengan capaian pada April 2025 sebesar Rp657 T dibandingkan pada April 2024 yang mencapai Rp719,9 T. Sementara itu, “Kewajiban utang jatuh tempo tahun ini Rp800,33 triliun, ditambah bunga total Rp1.353,18 triliun. Luar biasa! Sementara pendapatan pajak melambat dan belanja rutin melebihi belanja modal.” kata Esther. Padahal, lanjutnya, kebutuhan untuk membiayai program prioritas pada RAPBN 2026 sangat tinggi.
Esther merekomendasikan reformasi fiskal mendesak untuk mendorong aspek transparansi dan keadilan, diantaranya moratorium penambahan beban pajak seperti PPN dan PBB di tengah daya beli yang lemah; terapkan pajak kekayaan super kaya untuk redistribusi; revisi pemotongan TKD yang membuat pajak daerah melonjak; terapkan participatory budgeting dengan melibatkan masyarakat rentan; realokasi anggaran tidak produktif seperti insentif pejabat/DPR dan belanja militer ke sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan stimulasi konsumsi masyarakat; evaluasi kenaikan anggaran pertahanan; memprioritaskan anggaran pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru; alokasikan anggaran program prioritas secara bertahap sesuai kapasitas fiskal dan lakukan evaluasi secara berkala; serta revitalisasi industri manufaktur, penguatan rantai pasok domestik, dan transformasi UMKM ke skala menengah untuk kurangi sektor informal dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas guna mencegah kontraksi ekonomi lebih lanjut.