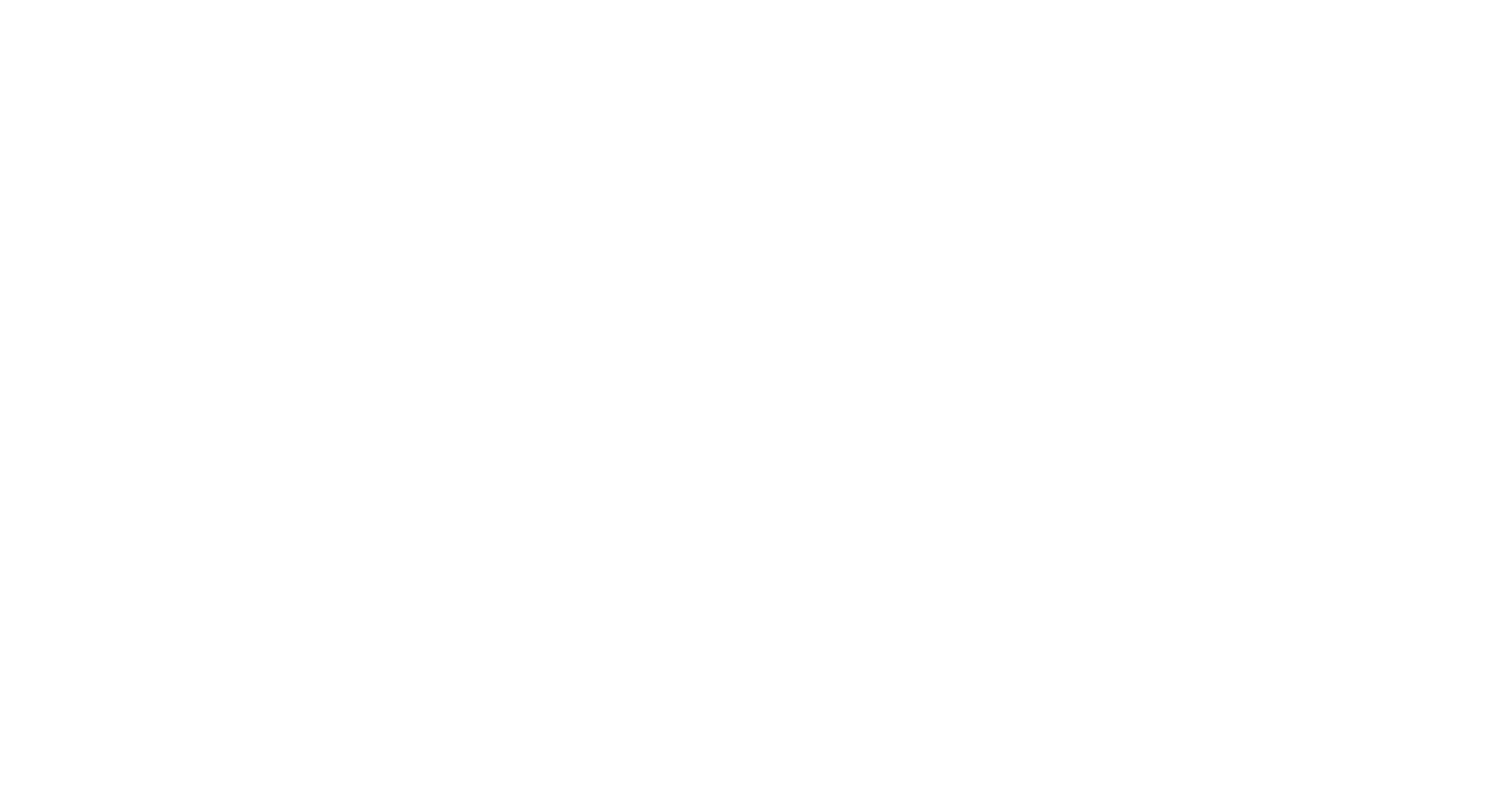Penulis: Pierre Bernando Ballo
Editor: Aria W. Yudhistira
RINGKASAN (Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI)
- Di balik euforia bonus demografi, Indonesia menghadapi ancaman populasi menua di mana jumlah penduduk usia non-produktif akan melampaui usia produktif. Hal ini akan menciptakan beban besar bagi generasi produktif yang harus menopang lebih banyak orang.
- Perlindungan hari tua sangat minim, terbukti dari rendahnya partisipasi masyarakat pada program jaminan pensiun, terutama di kalangan pekerja informal dan perempuan. Masalah ini diperparah dengan tidak adanya lembaga khusus yang mengadvokasi isu-isu terkait lansia setelah Komisi Nasional Lanjut Usia dibubarkan.
- Diperlukan reformasi kebijakan untuk memperluas cakupan jaminan hari tua dengan skema yang lebih fleksibel dan sensitif gender. Selain itu, pemerintah didesak untuk menghidupkan kembali lembaga khusus yang fokus merancang dan mengawasi kebijakan perlindungan bagi lansia.
Indonesia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-80. Delapan dekade berlalu, dan tiap tahun kita merayakan memori kolektif lintas-generasi akan bangsa yang bertambah tua. Seiring bertambahnya usia sebuah bangsa, bertambah juga usia penduduknya. Pertanyaan adalah siapa yang akan merayakan saat kita menginjak lanjut usia (lansia)?
Menurut Analisis Profil Penduduk Indonesia yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memasuki periode “bonus demografi” dari 2012 hingga 2035, dengan puncak yang diperkirakan terjadi pada 2020-2030. Pada 2030, diproyeksikan 68,5% dari total penduduk, atau sekitar 203,5 juta jiwa, berada pada usia produktif. Angkanya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Pada tahap ini, perekonomian diproyeksikan tumbuh pesat, dan produktivitas meningkat—setidaknya di atas kertas.
Tak dapat dipungkiri, narasi ini membanjiri setiap paparan pemerintah, seminar, presentasi, bahkan menjadi landasan berbagai kebijakan lintas sektor. Namun, tersembunyi di balik euforia tersebut, ada bom waktu yang seringkali terabaikan. Di dalamnya terdapat teka-teki sederhana untuk menjinakkannya, “apa yang akan terjadi setelah periode ‘kejayaan’ itu berakhir?”
Mulai 2030, proyeksi menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia non-produktif akan meningkat dan melampaui mereka yang di usia produktif. Dependency Ratio (DR) diperkirakan mencapai 51%. Artinya, dari setiap 100 orang, 51 di antaranya harus menggantungkan hidupnya pada 49 orang usia produktif yang menopang mereka. Seiring berjalannya waktu, perlahan namun pasti akan ada lebih banyak mulut yang harus diberi makan dibandingkan tangan yang bekerja.
Inilah yang kini populer disebut sebagai sandwich generation, generasi usia produktif yang “terimpit” dan harus menanggung beban dari dua ujung piramida demografi sekaligus. Namun, fakta yang seringkali diabaikan adalah bahwa generasi ini tidak lahir karena kegagalan perencanaan keuangan individu semata, tetapi berakar pada struktur kebijakan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi semua lapisan dalam piramida demografi. Karena itu, reformasi dibutuhkan, dan urgensinya tidak pernah sebesar sekarang.
Berbagai kebijakan yang ada saat ini sudah menyadari betapa pentingnya mempersiapkan lapisan bawah piramida demografi. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka yang berusia 0-15 tahun. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di usia lanjut usia (lansia), dan penduduk usia produktif yang menuju ke sana?
Pada 2045, diproyeksikan 20% penduduk Indonesia, atau sekitar 63 juta jiwa, berusia di atas 65 tahun. Ketika Indonesia memasuki tahap menua, banyak lansia yang dibiarkan tanpa perlindungan. Studi PRAKARSA (2024) menunjukkan bahwa saat ini hanya 4% penduduk lansia yang memiliki dan menikmati manfaat dari Skema Pensiun (Jaminan Pensiun/JP). Rendahnya tingkat partisipasi pada program BPJS Ketenagakerjaan juga terlihat pada usia kerja produktif, kategori Pekerja Penerima Upah (PPU), di mana tingkat partisipasi mereka pada dua program perlindungan hari tua, JP dan Jaminan Hari Tua (JHT), masing-masing hanya 8% dan 10%.
Tingkat partisipasi bahkan jauh lebih rendah bagi pekerja informal (Bukan Penerima Upah/BPU), dengan hanya 0,2% yang saat ini terdaftar dalam JHT. Bagi mereka, kemampuan membayar menjadi masalah terbesar, di mana 58,33% responden riset hanya sanggup membayar Rp60 ribu-Rp100 ribu per bulan untuk program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Masalah lainnya adalah tidak diwajibkannya partisipasi JP dan JHT bagi BPU. Akibatnya, ketika ada kenaikan gelombang PHK seperti yang terjadi belakangan, BPU terpaksa untuk mencairkan tabungan JHT mereka untuk kebutuhan sehari-hari, dan akibatnya mereka tidak memiliki sumber penghasilan saat memasuki usia tua.
Kesenjangan gender juga tampak jelas dalam implementasi program perlindungan hari tua. Studi PRAKARSA (2024) menunjukkan bahwa 97% responden perempuan menyatakan bahwa persiapan hari tua itu penting, namun mereka tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan pekerja perempuan, khususnya informal, umumnya dibayar jauh lebih rendah daripada laki-laki, dan sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kerja-kerja perawatan.
Tanpa perlindungan hari tua yang layak, yang terjadi adalah penduduk kita semakin miskin seiring bertambahnya usia. Hal ini juga dibuktikan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menunjukkan bahwa prevalensi kemiskinan tertinggi ada pada kelompok usia 60-74 tahun, dan di atas 75 tahun.
Persentase Kemiskinan Menurut Usia

Ket: Penentuan miskin berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten/Kota
Indonesia juga tidak memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab pada isu lansia. Melalui Peraturan Presiden No. 112/2020, pemerintah membubarkan Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia). Sebelumnya, Komnas Lansia merupakan lembaga non-struktural yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, berada langsung di bawah Presiden, dan memiliki peran penting sebagai pengawas perencanaan kebijakan lintas sektor serta perumusan regulasi terkait isu lansia.
Pembubaran tersebut memicu kritik publik, mengingat kuatnya keterlibatan Komnas Lansia dalam berbagai kebijakan dan regulasi lintas sektor mengenai lansia. Pembubarannya juga menandai kemunduran dalam advokasi nasional terkait jaminan hari tua, dan jelas berdampak signifikan dalam permasalahan demografi yang kita hadapi saat ini.
Reformasi Kebijakan untuk Jaminan Hari Tua
Indonesia akan memasuki masa penuaan. Oleh karenanya, sangat penting agar desain kebijakan sosial mengintegrasikan perspektif lansia ke dalamnya. Kini, sudah waktunya pemerintah mereformasi sistem perlindungan hari tua yang ada saat ini melalui beberapa opsi kebijakan.
Pertama, pemerintah harus memperluas cakupan dan mewajibkan partisipasi program JP dan JHT bagi pekerja informal (BPU), dan mengembangkan skema cost-sharing tripartit antara pemerintah, swasta, dan pekerja untuk membiayai premi asuransi. Pemerintah dapat meniru model baik yang sudah diterapkan baru-baru ini melalui pemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Namun, opsi ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan dari APBN kepada BPJS Ketenagakerjaan, serta perubahan regulasi pada UU No. 40/2004 tentang SJSN yang akan memakan waktu.
Kedua, memperkenalkan premi asuransi dengan tarif flat namun dengan ketentuan pembayaran yang fleksibel, khususnya untuk mengakomodasi pekerja informal (BPU) yang berpendapatan tidak menentu. Skema ini bisa berlaku baik pada JHT maupun JP. Salah satu contoh baik di negara lain adalah skema Universal Pension Scheme (UPS) Bangladesh yang menerapkan mekanisme pembayaran fleksibel dan tidak dipatok pada waktu-waktu tertentu.
Ketiga, memperkenalkan skema pensiun yang sensitif gender untuk membantu pekerja perempuan menyiapkan perencanaan hari tua. Salah satunya dengan menghadirkan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berbasis means-tested yang memprioritaskan pekerja perempuan untuk membayar premi asuransi mereka.
Keempat, menghidupkan kembali Komnas Lansia dan memperluas perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga terlibat dalam perencanaan kebijakan lintas sektor terkait isu lansia.
Kesimpulan
Saat kita merayakan ulang tahun delapan dekade bangsa kita, penting untuk memastikan bahwa bangsa ini juga merayakan kita ketika memasuki usia 80 tahun. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kita juga mencapai “kemerdekaan” di usia itu, tanpa harus membebani generasi yang berada di bawah kita.
***
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Nasib Lansia setelah Bonus Demografi Berakhir,” Baca selengkapnya di sini: Katadata.co.id