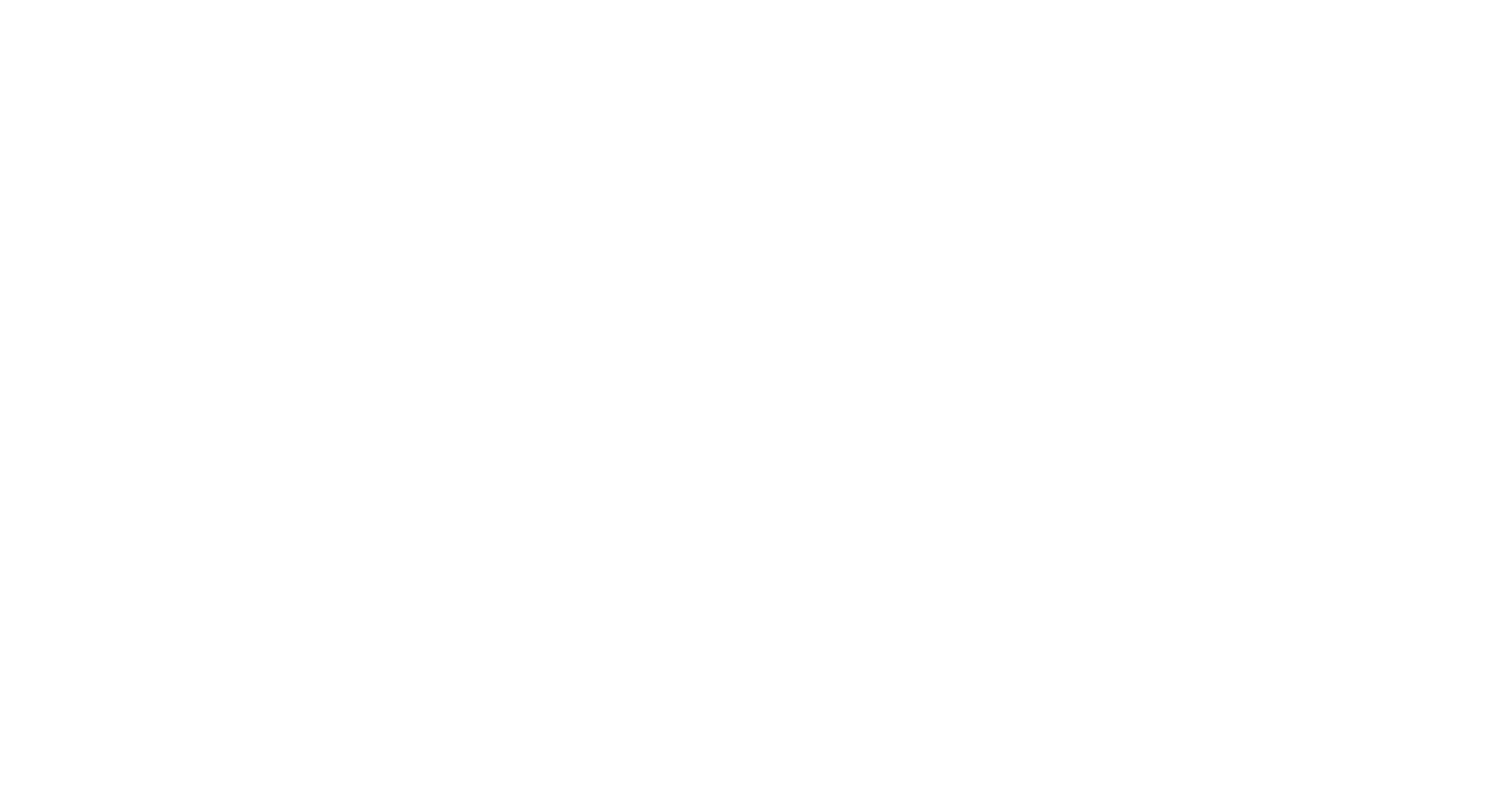By: Ari Wibowo
Periset di Prakarsa. Saat ini ia juga aktif di IPB University sebagai Kepala Unit Sistem Informasi Pengelolaan Pengetahuan di Pusat Studi Agraria, serta Asisten Divisi Kependudukan, Kajian Agraria, dan Ekologi Politik (KAREP) di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat – Fakultas Ekologi Manusia.
Gerakan rakyat Pati mengajarkan kita soal nasionalisme warga. Nasionalisme yang lahir dari keberanian melawan ketidakadilan.

Ringkasan Berita
- Gerakan warga Pati adalah anomali di tengah kelesuan spirit Reformasi yang kian meredup.
- Demosntrasi warga Pati lahir dari solidaritas autentik antar-desa.
- Bahan bakar gerakan rakyat Pati sederhana: rasa keadilan dan kemanusiaan yang dilukai.
KERESAHAN publik atas dampak pembangunan nasional selama hampir satu setengah dekade terakhir seakan-akan hanya menjadi bara kecil yang tak kunjung menyala. Ketimpangan sosial-ekonomi melebar, ruang hidup dirampas, dan konflik agraria makin struktural.
Para pembela hak asasi manusia dan lingkungan dibungkam, hukum dijadikan alat politik, serta demokrasi dipersempit. Namun semua itu belum menjelma gelombang perlawanan yang bisa mengguncang tatanan politik nasional.
Spirit Reformasi 1998 pun kian meredup, ditelikung oleh anak kandungnya sendiri.
Dari tengah kelesuan itulah Pati, sebuah kota di pesisir utara Jawa Tengah, memunculkan anomali. Warganya berbondong-bondong turun ke jalan, menentang kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski gerakan mereka sempat meredup, pada awal September ini, ratusan warga Pati datang ke Ibu Kota. Mereka berdemonstrasi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi yang dilakukan sang Bupati.
Protes itu bukan digerakkan partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat, melainkan lahir dari solidaritas autentik antardesa. Gerakan yang jarang muncul di era demokrasi yang kian terkendali. “Kenapa rakyat Pati bisa muncul dan masif? Apa ini embrio baru people power?” begitu banyak aktivis gerakan sosial bertanya-tanya.
Esensi People Power
Dalam literatur klasik, people power adalah puncak partisipasi warga ketika saluran resmi tak lagi berfungsi. Victoria A. Bautista (1986), melalui artikel “People Power as a Form of Citizen Participation”, menyebutnya sebagai jaminan agar kehendak rakyat tetap terwujud meski kanal formal ditutup. Di Filipina pada 1986, barikade massa di jalanan EDSA menjatuhkan Ferdinand Marcos. Di Indonesia, Reformasi 1998 menggulingkan Soeharto.
Namun di Pati, rakyat tidak hendak menjatuhkan rezim nasional. Mereka hanya menuntut pemimpin lokal bertanggung jawab atas mandat konstitusionalnya. Perlawanan itu tumbuh organik tanpa patronase tokoh besar atau rekayasa partai politik. Kekuatannya lahir dari solidaritas antarwarga desa yang merasa dicekik kebijakan tak adil.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa kekuatan rakyat sejati tak memerlukan panggung megah atau komando elite. Bahan bakarnya sederhana: rasa keadilan dan kemanusiaan yang dilukai.
Perlawanan rakyat Pati terhadap pajak sebenarnya bukan hal baru. Sejarah panjang daerah ini memperlihatkan pola berulang. Sejak abad ke-16, mereka menolak menjadi sapi perah penguasa. Di era Kerajaan Demak, kenaikan pajak hasil bumi hingga 30 persen memicu protes rakyat Tombronegoro. Ketika Kerajaan Pajang kembali menaikkan pajak 20 persen, banyak petani memilih eksodus.
Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung dan Amangkurat I membebankan upeti beras hingga 50 persen. Kebijakan ini membuat Adipati Pragola II dan III memimpin pemberontakan besar yang mengguncang pusat kekuasaan.
Ketika VOC masuk, bea dagang dan pajak pelabuhan yang mencekik membuat rakyat Pati terlibat dalam Geger Pecinan. Di era kolonial modern, beban pajak tanah yang dipatok Daendels dan Raffles hingga 30 persen dari hasil panen makin menjerat. Masa Tanam Paksa menambah penderitaan: beban pajak bisa setara dengan dua pertiga hasil panen.
Namun rakyat Pati tetap memilih melawan, bahkan jika harus dengan cara pasif seperti mogok tanam. Watak anti-ekstraksi itu mencapai bentuk paling radikal pada akhir abad ke-19 lewat gerakan Saminisme. Dipelopori Samin Surosentiko, kaum Samin menolak membayar pajak kolonial dengan sikap non-kooperatif. Pajak, bagi mereka, adalah simbol perampasan hak atas tanah.
Sejarah itu menunjukkan satu benang merah: pajak bisa menjadi kontrak sosial yang kuat bila adil dan transparan, tapi berubah menjadi pemicu perlawanan bila sewenang-wenang.
Pajak dan Mentalitas Kolonial
Hingga hari ini, warisan sistem perpajakan kolonial masih membayangi Indonesia. Mentalitas koersif dan ekstraktif tetap dominan. Negara diposisikan sebagai entitas yang berhak mengambil dari rakyat, sedangkan rakyat wajib memberi. Logika ini tak jauh berbeda dengan cultuurstelsel era Belanda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut pajak sebagai “instrumen gotong-royong” yang spiritualitasnya setara dengan zakat. Pernyataan itu menuai kritik. Pajak, sejatinya, adalah kewajiban sipil yang berbasis kontrak sosial antara negara dan warga.
Pajak membutuhkan legitimasi dari transparansi dan akuntabilitas. Membandingkannya dengan zakat, yang berlandaskan keikhlasan dan hubungan vertikal dengan Tuhan, justru mengaburkan hak rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban negara.
Kenaikan PBB di Pati tak bisa dilepaskan dari politik anggaran nasional. Pemotongan dana transfer ke daerah sebesar Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 serta rencana pemangkasan 31 persen—sekitar Rp 270 triliun—dalam Rancangan APBN 2026 memaksa pemerintah daerah mencari sumber penerimaan baru. Cara paling instan adalah menaikkan pajak.
Namun rakyat akhirnya tak mau lagi diam. Diam bukan berarti setuju, melainkan menunggu momentum. Pati menunjukkan bahwa ledakan bisa terjadi kapan saja. Percikan perlawanan ini bahkan merambat ke daerah lain, seperti Jombang, Cirebon, hingga Bone.
Sayangnya, fungsi pengawasan legislatif kerap tumpul. DPR ataupun DPRD bungkam. Senyapnya suara kritis atas korelasi antara pemotongan anggaran pusat dan penderitaan rakyat di daerah menjadi penanda matinya representasi politik. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dan baru didengar ketika amuk meledak.
Perlawanan rakyat Pati, pada akhirnya, bukan hanya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan. Ia adalah bentuk nasionalisme dan cinta Tanah Air yang diwujudkan dalam keberanian melawan ketidakadilan—bahkan jika ketidakadilan itu datang dari pemerintah sendiri.
Gerakan rakyat Pati adalah contoh nasionalisme warga, bukan nasionalisme ala negara. Nasionalisme ini lahir dari keberanian melawan ketidakadilan, bahkan ketika ketidakadilan itu datang dari para pemimpin. Nasionalisme ini mengajarkan kita bahwa membela negara kadang berarti melawan kebijakan negara dan penguasanya.
Gerakan Pati adalah lonceng peringatan bahwa kekuatan rakyat sejati masih ada dan bisa meledak kapan saja.
Sumber: Tempo.co