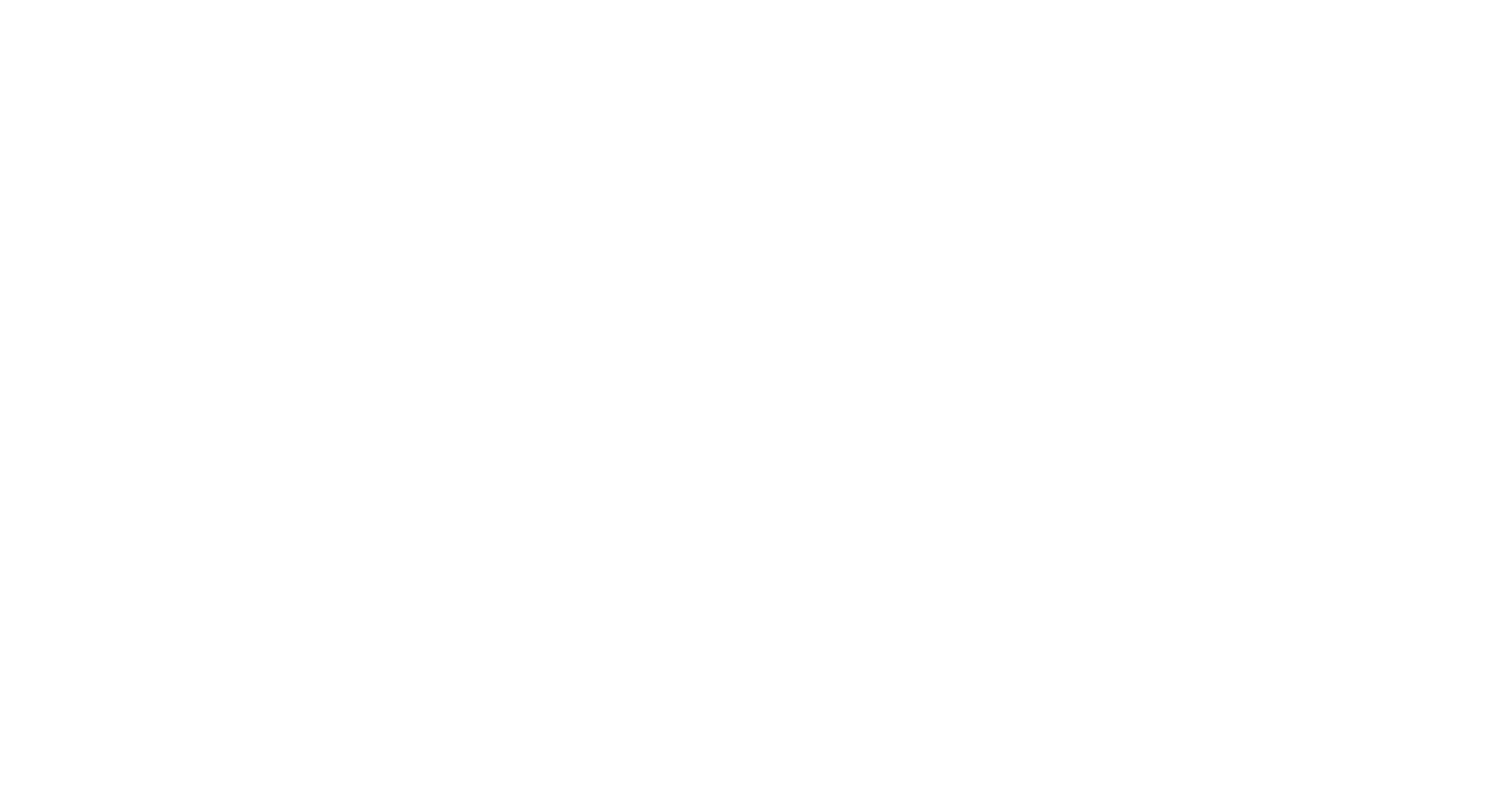Setyo Budiantoro
Fellow IDEAS–UID MIT Sloan School of Management, Advisory Committee Fair Finance Asia, dan SDGs–ESG Expert di Indonesian ESG Professional Association (IEPA) dan The Prakarsa
Delapan puluh tahun setelah Proklamasi, Indonesia berada di persimpangan sejarah yang hanya datang sekali dalam satu generasi.
Di hadapan terbentang peluang langka: menjadi negara maju sebelum seratus tahun kemerdekaan, memimpin rantai pasok global yang tengah bergeser, dan mengambil posisi strategis dalam transisi dunia menuju ekonomi rendah karbon.
Pilihan arah telah jatuh pada kapal besar bernama developmental state (negara pengarah pembangunan)—negara yang hadir dengan kendali kuat, mengarahkan industri, membangun infrastruktur raksasa, dan mengorkestrasi investasi layaknya konduktor yang menuntun harmoni orkestra.
Namun, setiap pelaut berpengalaman tahu bahwa peta bukanlah lautan. Garis-garis tegas di meja perencana tidak selalu menangkap arus bawah, perubahan angin, atau awan gelap di kejauhan.
Developmental state cenderung seeing like a state—melihat dari ketinggian, di mana segalanya tampak teratur, seperti yang disampaikan James Scott. Penting, tetapi tidak cukup.
Agar kapal besar ini tiba di pelabuhan sejarah, perlu ditambahkan satu lensa lagi: seeing like a citizen. Ini adalah kemampuan menangkap realitas sehari-hari yang sering luput dari dokumen resmi: tanda-tanda daya beli yang berubah di pasar, adaptasi petani terhadap cuaca, atau inovasi kecil yang lahir di bengkel desa. Semua itu adalah potongan mozaik yang, jika dirangkai, memberi peta yang lebih hidup dan akurat.
Peristiwa demonstrasi besar yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Pati baru-baru ini menjadi pengingat bahwa tanda-tanda itu tidak bisa diabaikan.
Gelombang suara rakyat adalah bagian dari peta yang hidup—memberi arah, mengoreksi haluan, dan menuntut agar kebijakan tidak hanya tepat di atas kertas, tetapi juga tepat di hati dan realitas masyarakat.
Sejarah kita pernah memberi contoh yang kuat. Soekarno, dalam perannya sebagai “penyambung lidah rakyat”, bukan sekadar juru bicara.
Ia turun ke sawah, berdialog dengan Marhaen—petani kecil yang menjadi simbol rakyat jelata—dan dari sana memetik arah politik ekonomi. Ia memandang dari atas untuk membaca arah zaman, tetapi juga melihat dari bawah untuk memastikan arah itu berpijak pada kenyataan.
Pendekatan ini—berdiri di tengah rakyat namun mampu membaca seluruh sistem—adalah inti dari kepemimpinan yang peka terhadap tanda-tanda perubahan. Dalam bahasa hari ini, inilah kemampuan sensing (kepekaan menangkap sinyal perubahan): membaca tanda-tanda lemah sebelum menjadi gelombang besar.
Dan lebih jauh lagi, presencing yaitu menghadirkan masa depan yang ingin diwujudkan ke dalam keputusan hari ini, pemaknaan yang dinisiasi Otto Scharmer. Ini adalah kemampuan tidak hanya bereaksi pada perubahan, tetapi juga menjemput arah baru sebelum ia tiba.
Tanpa sensing dan presencing, kapal bisa terjebak dalam blindspot (titik buta) yaitu merasa aman karena semua indikator terlihat hijau, padahal badai sedang membentuk diri di cakrawala.
Dan sejarah juga memberi peringatan yang tak kalah jelas: negara yang terlalu lama hanya seeing like a state mudah terperangkap dalam peta yang ia gambar sendiri, terkurung dalam “ruang gema” (echo chamber) yang meninabobokan, membuatnya percaya segalanya terkendali, meski tanda-tanda di luar temboknya berkata sebaliknya.
Di dalam peta itu, sawah masih hijau padahal di lapangan sudah menjadi deretan rumah. Di laporan resmi, stok pangan tercatat aman berbulan-bulan, padahal di pasar harga beras sudah merangkak naik.
Dalam grafik, angka kemiskinan terlihat menurun, tetapi di gang sempit ibu-ibu mulai mengurangi porsi makan anaknya.
Di halte, sekelompok anak muda bercanda untuk menutupi kegelisahan karena panggilan kerja tak kunjung datang. Daya beli melemah, kelas menengah tergerus, dan daya saing nasional pelan-pelan terkikis.
Apa yang terjadi di Pati mengingatkan kita bahwa suara rakyat bukanlah gangguan yang harus diredam, melainkan kompas yang perlu dibaca dengan saksama.
Ia menunjukkan arah yang terkadang luput dari peta resmi, tetapi sangat nyata terasa di lapangan. Dalam dinamika demokrasi, gelombang aspirasi publik bukan hanya koreksi, tapi juga energi yang bisa memperkuat keputusan negara.
Kebijakan, oleh karena itu, tidak boleh berhenti sebagai rumusan di balik meja birokrasi; ia harus menjelma menjadi denyut yang hidup—dirasakan, dipahami, dan dijalankan bersama masyarakat.
Untuk menjaga agar arah besar pembangunan tidak menyimpang, serta memastikan daya adaptif bangsa tetap tajam menghadapi perubahan, tiga langkah strategis berikut perlu segera dihidupkan.
Pertama, membangun “Radar Perubahan Nasional”—sistem terpadu yang tidak hanya bergantung pada data resmi pemerintah, tetapi juga menangkap sinyal dini dari masyarakat, pasar, dan daerah.
Model ini bisa mengadaptasi praktik Whole-of-Government Integrated Risk Management System di Singapura, dimana seluruh kementerian dan lembaga berbagi “radar kebijakan” secara real time. Dengan begitu, potensi badai dapat terbaca lebih cepat, dan respons kebijakan bisa diambil secara presisi, tepat waktu, dan terukur.
Kedua, mengadakan Policy Review Forum setiap enam bulan, mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil.
Forum ini menjadi ruang bersama untuk menguji ulang asumsi, menemukan celah implementasi, dan menyesuaikan langkah dengan realitas terbaru.
Korea Selatan melakukan hal serupa melalui Economic Policy Review Meetings lintas sektor, memastikan kebijakan tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika global maupun kebutuhan domestik.
Ketiga, membentuk Indeks Kerja Sama Nasional untuk mengukur seberapa padu pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bergerak menuju tujuan bersama.
Indeks ini dapat mengacu pada kerangka Policy Coherence for Sustainable Development di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), namun diperluas agar memotret keselarasan lintas dimensi—lingkungan, inklusi sosial, dan pemerataan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan Goal 17 Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan kemitraan multi-pihak sebagai mesin utama pencapaian agenda pembangunan.
Dampaknya tidak berhenti pada koordinasi yang rapi di atas kertas: hambatan antar-lembaga dapat diidentifikasi lebih cepat, potensi kolaborasi baru terpetakan, dan sumber daya diarahkan ke titik-titik yang memberi hasil terbesar. H
asil akhirnya adalah kebijakan yang konsisten lintas sektor, program yang sinkron antara pusat dan daerah, dan manfaat pembangunan yang lebih merata lintas generasi.
Sejarah memberi kita kapal besar, kompas yang jelas, dan ombak yang mengarah mendukung. Tetapi pelabuhan tujuan tidak akan menunggu.
Tantangan kita bukan hanya untuk mengarahkan kapal, tetapi untuk memimpin dengan kedua mata terbuka: satu menjaga arah besar agar kita tidak kehilangan tujuan, satu lagi memastikan tanda-tanda kecil yang bisa mengubah segalanya terbaca tepat waktu.
Karena dalam sejarah, bukan hanya badai besar yang menenggelamkan kapal, tetapi juga gelombang kecil yang diabaikan terlalu lama. Pemimpin besar bukan hanya mengarahkan kapal, tapi juga mendengarkan lautan.
Dan mungkin, inilah saatnya Indonesia berlayar dengan seluruh indranya—agar ketika kita tiba di daratan sejarah itu, kita tidak hanya selamat, tetapi juga sampai dengan kapal yang utuh, awak yang teguh, dan masa depan yang layak kita wariskan.
Sebab sejarah tidak menunggu, dan ombak zaman hanya berpihak pada mereka yang benar-benar siap membaca arahnya.
Sumber : Tribunner