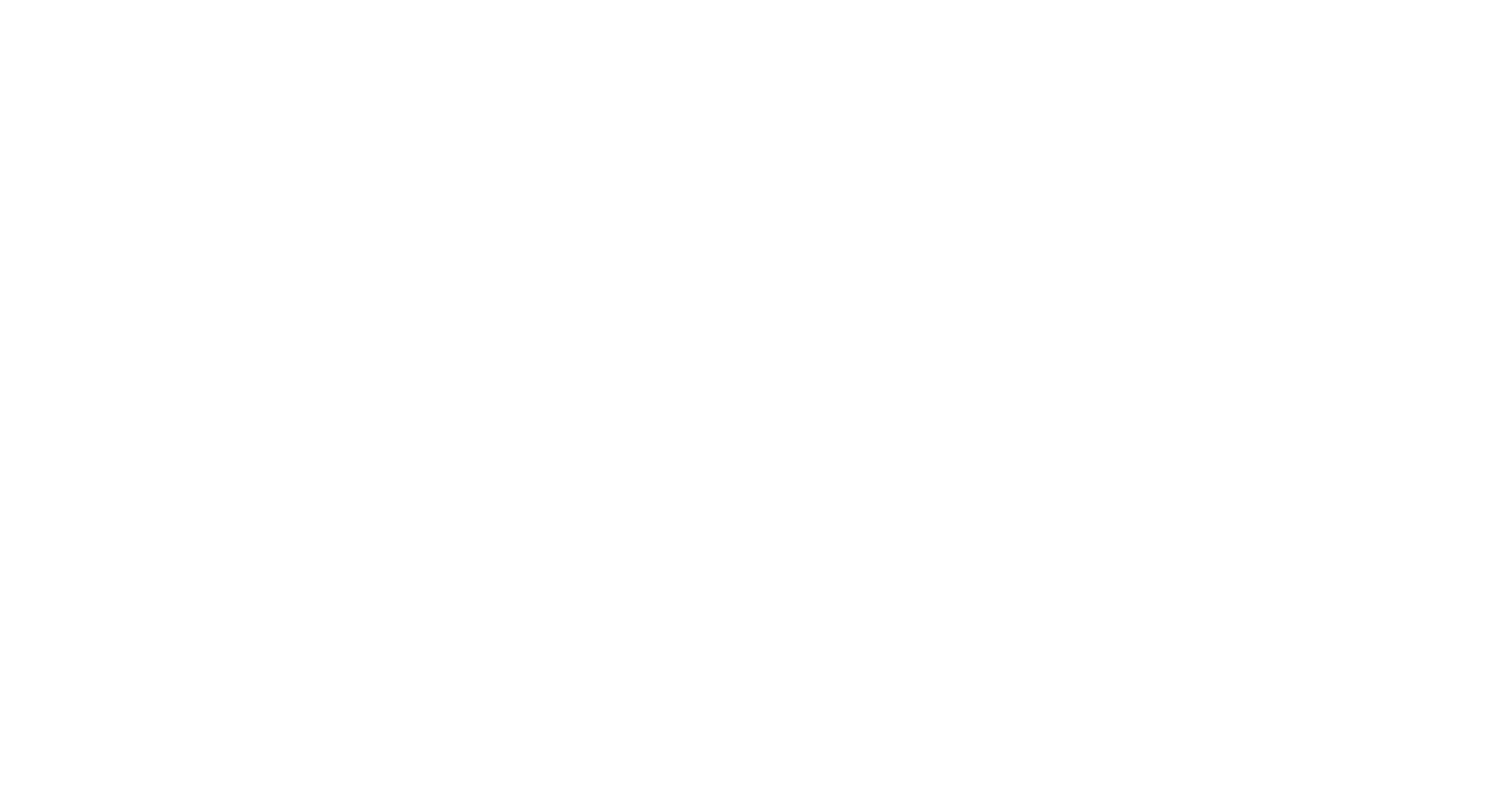Oleh: Ah Maftuchan – Direktur Eksekutif The PRAARSA
SWASEMBADA pangan menjadi agenda pembangunan lintas batas pemerintahan di Indonesia. Setiap kali presiden berganti, wacana ini selalu muncul. Persoalannya, realisasi program swasembada pangan jauh panggang dari api. Muncul pertanyaan: apakah hal ini akan terulang pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Dalam Asta Cita yang memuat delapan misi prioritasnya, Prabowo mencantumkan swasembada pangan. Dalam agenda 100 hari pemerintahan yang disebut quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Prabowo menetapkan pencetakan lahan sawah, peningkatan produktivitas lahan pertanian, dan pengembangan lumbung pangan sebagai langkah menuju swasembada. Bahkan ada rencana penghentian impor sejumlah komoditas pangan. Sebagian program dan rencana ini mulai terwujud meski hasilnya belum terbukti.
Jika melihat ke belakang, dua pemerintahan sebelumnya menetapkan agenda swasembada pangan dengan cara berbeda. Pada era Joko Widodo, misalnya, ada janji swasembada pangan tercapai dalam dua-tiga tahun. Tapi, pada kenyataannya, Indonesia tetap harus mengimpor beras jutaan ton per tahun. Artinya, swasembada pangan di era Jokowi dapat disimpulkan gagal.
Ada dua faktor penyebab kegagalan swasembada pangan di era Jokowi. Yang pertama adalah faktor iklim. El Niño menghantam produktivitas padi. Kondisi ini berat untuk dikendalikan ketika inovasi teknologi pertanian masih minim. Yang kedua adalah tata kelola. Agenda swasembada pangan rupanya dikejar dengan pendekatan jangka pendek yang terbungkus kepentingan politik. Hal ini tecermin dari proyek lumbung pangan atau food estate yang terbukti gagal memproduksi pangan. Di sisi lain, food estate menimbulkan eksternalitas negatif pada lingkungan dan sosial.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek swasembada pangan juga gagal. Pemerintahan Yudhoyono kala itu menargetkan swasembada beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Caranya juga membangun food estate bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate seluas 1,23 juta hektare di Papua serta proyek serupa di Bulungan, Kalimantan Timur (kini Kalimantan Utara), dan Ketapang, Kalimantan Barat. Sampai akhir masa pemerintahannya, Yudhoyono tak bisa mewujudkan swasembada pangan.
Era Soeharto berbeda. Melalui pendekatan Revolusi Hijau, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada 1984. Namun keberhasilan itu tidak bertahan lama karena pada 1990 Indonesia kembali mengimpor beras. Revolusi Hijau hanya ampuh sesaat. Yang jelas, banyak masalah muncul, seperti kerusakan lingkungan akibat pupuk dan pestisida kimia. Bibit padi hasil rekayasa genetik juga merangsang munculnya hama wereng. Melihat kondisi itu, Soeharto akhirnya potong kompas dengan menjalankan proyek lahan gambut 1 juta hektare di Kalimantan Tengah pada 1996. Tapi proyek ini juga gagal total.
Jika becermin pada para pendahulu, ada kesamaan pendekatan berikut hasilnya. Para presiden sebelum Prabowo menjalankan kebijakan yang bersifat short-term, bad governance, serta top-down and state-driven. Target swasembada pangan yang tercapai dalam dua-empat tahun memperlihatkan pendekatan jangka pendek yang sangat dipengaruhi kepentingan politik. Padahal swasembada pangan harus diletakkan sebagai agenda negara-bangsa sehingga kalis dari pragmatisme politik.
Target Prabowo mencapai swasembada pangan dalam tiga-empat tahun memperlihatkan pengulangan ambisi presiden-presiden sebelumnya. Tapi, agar hasilnya berbeda, sebelum menjalankan program, Prabowo harus memastikan fondasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan, termasuk dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan di bidang pangan lewat pemberantasan praktik koruptif, kolusi, dan nepotisme di bidang pangan. Kementerian/lembaga hingga otoritas pangan di daerah yang berkinerja buruk perlu pula dibenahi.
Yang juga harus diperhatikan adalah selalu digunakannya pendekatan top-down dalam program swasembada pangan. Semua kebijakan datang dari pemerintah pusat. Hal ini memperlihatkan pemerintah daerah tidak berperan aktif. Dibanding pemerintahan sebelumnya, Prabowo mungkin akan lebih kuat menerapkan pendekatan komando dari pusat ke daerah. Padahal, secara natural, kondisi lahan, komoditas, dan varietas di suatu daerah berbeda dengan daerah lain.
Jangan lupa, Indonesia juga telah menjalankan desentralisasi sehingga proyek swasembada pangan seharusnya menggunakan pendekatan gabungan sentralistik dan desentralistik. Masih dominannya pendekatan state-driven—hampir semua agenda swasembada pangan didorong dan ditentukan oleh negara—bisa kembali menggagalkan tujuan program ini. Sebagai contoh yang harus diwaspadai, model food estate yang terbukti gagal pada era Soeharto terus diulang di era Yudhoyono dan Jokowi, dan (akan) kembali pada masa pemerintahan Prabowo.
Pada 100 hari pemerintahan Prabowo, agenda quick win swasembada pangan baru sampai pada tataran cetak sawah atau lahan. Sementara itu, agenda krusial seperti pembentukan petani baru, pengembangan inovasi produksi pertanian, dan kebijakan pendukung lain belum terlihat. Yang lebih parah, partisipasi petani dalam agenda swasembada pangan sangat minim. Petani hanya menjadi obyek dari satu proyek ke proyek lain.
Menyitir pendapat Baldy dan Kruse (2019), untuk memastikan adanya transformasi pangan yang berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktor lokal seperti petani. Perlu ada semangat food democracy dalam agenda swasembada pangan, menjadikan petani subyek sekaligus obyeknya. Sayangnya, jika melihat data, terjadi penurunan jumlah pekerja usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Usia pekerjanya pun makin tua dan jumlah lahan yang digarap makin sempit.
Sensus pertanian Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah usaha pertanian perorangan menurun dari 31,7 juta pada 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau anjlok 7,45 persen. Jumlah petani milenial (berusia 19-39 tahun) hanya 6,1 juta atau sekitar 21,9 persen, sementara petani berumur 40-65 tahun ke atas sebanyak 23,2 juta atau 78,1 persen dari total petani Indonesia. Jumlah petani gurem dengan lahan di bawah 0,5 hektare naik dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023.
Agar swasembada pangan tercapai, Prabowo perlu memperkuat program dan kebijakan yang memihak petani. Contohnya dukungan modal usaha tani, bantuan alat-mesin pertanian, percepatan reforma agraria dan redistribusi lahan, pengembangan bibit lokal, bantuan tunai pembelian pupuk dan bibit, asuransi gagal panen, serta peningkatan keterampilan bercocok tanam. Pemerintah juga harus mengembangkan penghiliran produk pertanian dan menjadi off-taker produk pertanian sembari menciptakan rantai pasok komoditas yang lebih adil.
Makan bergizi gratis, proyek unggulan Prabowo, juga harus diintegrasikan dengan program swasembada pangan. Makan bergizi gratis hanya akan menjadi bumerang secara fiskal jika bahan makanannya tidak dapat disuplai dari dalam negeri. Impor pangan untuk proyek itu akan berdampak negatif pada pencapaian swasembada pangan.
Dari catatan tersebut, kita tentu tidak ingin mengulangi kegagalan seraya mengharapkan hasil berbeda dari pendekatan yang sama. Jangan seperti yang dikatakan Albert Einstein: “Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results”. Karena itu, agenda swasembada pangan memerlukan pendekatan baru yang tertata baik, inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan agar sukses dan tak hanya menjadi lagu populis pemerintahan baru.
***
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Majalah Tempo edisi 2 Februari 2025 dengan judul “Lagu Pop Swasembada Pangan“. Baca selengkapnya di sini: Koran Tempo