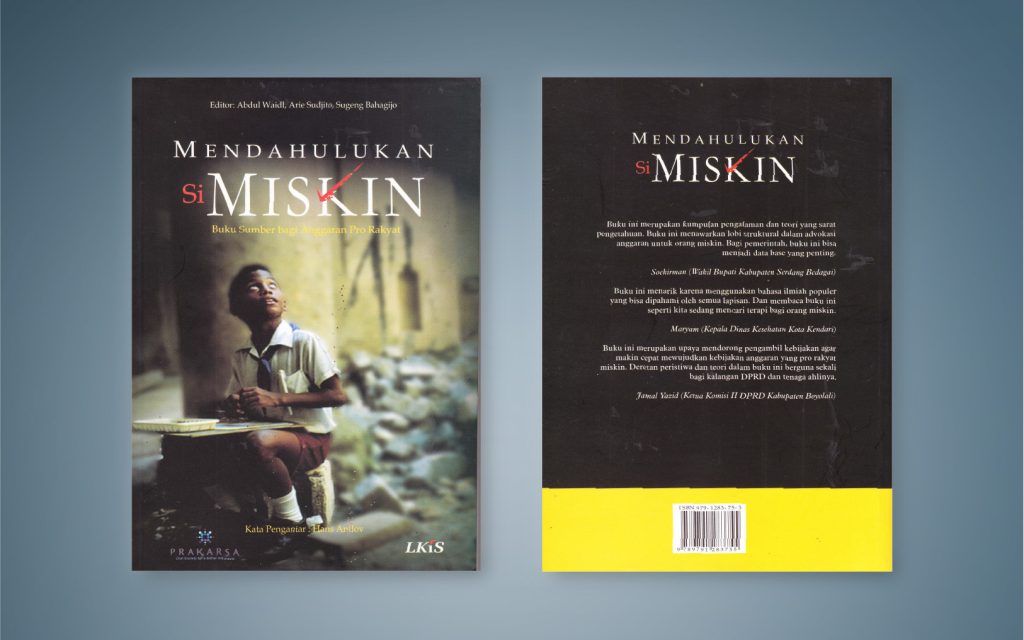
Buku ini adalah buku yang sangat penting tentang bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sipil di Indonesia secara bersama-sama berupaya agar lebih banyak dana tersedia untuk orang miskin dan keluarga-keluarga bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara merancang anggaran pro-poor di tingkat daerah dan nasional serta memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan disalurkan kepada orang miskin.
Krisis finansial yang mulai tahun 1997 telah meninggalkan jejak yang mendalam pada perekonomian Indonesia. Rupiah merosot dengan cepat, dan hingga kini belum pulih kembali. Meski suatu rejim demokratis telah dimulai pada tahun 1998, kerangka hukum bagi pembangunan ekonomi lokal masih tetap kompleks. Investasi langsung global (FDI) lebih memilih China, India dan Vietnam daripada Indonesia, dan berlanjutnya ketidakpastian di sektor-sektor pemerintahan semakin menyulitkan upaya menarik investor dalam negeri. Perekonomian untuk lima tahun ke depan diprediksi oleh pemerintah akan tumbuh sebesar enam persen per tahun. Banyak orang yakin bahwa ini adalah prediksi yang terlalu optimis. Pertumbuhan yang lambat berarti bahwa Indonesia akan tetap menjadi suatu negara dengan angka kemiskinan yang tinggi. Hampir separuh keluarga Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari dua dollar per hari, dan sekitar 15 persen diklasifikasikan sebagai orang miskin. Terdapat kebutuhan yang urgen akan adanya kebijakan pengentasan kemiskinan yang berpihak pada keluarga dan masyarakat miskin.
Apa penyebab kemiskinan? Tidak ada konsensus global tentang hal ini: para ahli di dalam dan di luar Indonesia saling beradu argumentasi. Singkatnya, paling sedikit terdapat empat faktor yang bekerja di sini, dan seringkali dalam bentuk kombinasi dua atau lebih dari faktor-faktor tersebut.Yang pertama dan paling jelas adalah tidak adanya akses ke pasar kerja. Jika suatu keluarga tidak mendapatkan pekerjaan – apapun alasannya – di negara tanpa kebijakan asuransi, ia akan menjadi keluarga miskin. Dengan demikian, salah satu strategi utama pengentasan kemiskinan adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan menumbuhkan perekonomian. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat. Jika seorang petani harus menjual tanahnya untuk kepentingan pembangunan atau suatu rumah tangga tidak memperoleh perlindungan yang memadai terhadap bencana alam dan bencana buatan manusia, kemungkinannya sangat besar mereka adalah miskin atau akan menjadi miskin. Ketiga, sebuah keluarga bisa menjadi miskin karena pelayanan sosial yang tidak memadai. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas masih tidak dapat diakses di beberapa bagian Indonesia. Anggaran pemerintah tidak selalu dialokasikan dengan semestinya atau tidak menjangkau rumah tangga sasaran. Korupsi dan penyalahgunaan dana publik dapat pula menjadi penyebab tidak langsung dari kemiskinan, sebab dana yang mestinya digunakan untuk mengatasi kemiskinan tidak menjangkau kaum miskin. Sebab keempat mengapa beberapa keluarga hidup miskin agak lebih sulit sebab hanya secara tidak langsung mempengaruhi kemiskinan, yaitu tidak diikutsertakan di dalam proses kebijakan. Seperti argumentasi yang diajukan oleh Amartya Sen dan lainnya, kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan keuntungan material, melainkan juga tentang marjinalisasi, ekslusi dan kurangnya pemberdayaan. Dengan demikian pengentasan kemiskinan perlu juga mengacu pada pemenuhan kebutuhan lain selain kebutuhan materi, termasuk kebutuhan sosial dan politik.
Lalu apa saja kebijakan yang diperlukan untuk mengentaskan dan keluar dari kemiskinan? Pada dasarnya, ada dua aliran pemikiran. Pertama adalah teori bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan membantu rakyat mengatasi kemiskinan mereka (pro-growth). Lapangan kerja menjadi jalan keluar utama dari kemiskinan, yang hanya dapat diciptakan melalui pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ini dengan demikian memfokuskan diri pada liberalisasi pertumbuhan ekonomi, dengan membiarkan “pasar” mengurus pengentasan kemiskinan. Hal ini terkadang dicirikan sebagai kebutuhan akan adanya kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan yang akan “menetes ke bawah” kepada kaum miskin dalam bentuk lapangan kerja dan penciptaan penghasilan. Upaya pemerintah yang utama adalah memperkuat peluang ekonomi dan lembaga-lembaga perekonomian, serta membiarkan kewirausahaan dan inovasi satu per satu keluarga memastikan keuntungan ekonomi mereka.
Aliran pemikiran yang kedua tentang pengentasan kemiskinan didasarkan pada kebijakan pro-poor yang peka terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini beragumentasi bahwa pasar tidaklah netral atau adil bagi semua. Kekuatan-kekuatan pasar dapat menciptakan marjinalisasi dan ketidaksetaraan yang lebih parah. Kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetap berada di luar atau termarjinalisasikan oleh proses pertumbuhan. Tidak semua orang berangkat dari titik tolak yang sama dalam kehidupannya dan keadaan hidupnya akan mempengaruhi peruntungan dan kekayaannya (atau ketiadaan kekayaan tersebut). Kebijakan pro-pertumbuhan gagal mempertimbangkan bagaimana perbedaan-perbedaan dalam hal kondisi sosial dan ekonomi di tempat-tempat yang berlainan dapat mempengaruhi dampaknya. Diperlukan kebijakan redistribusi dan tindakan afirmatif yang secara aktif dan eksplisit menangani ketidaksetaraan dari pasar bebas.
Namun demikian, terdapat pula bukti bahwa kebijakan pro-poor yang berdiri sendiri tanpa pertumbuhan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Hanya melindungi kaum miskin dalam bentuk subsidi atau hibah belum tentu mengangkat mereka dari kemiskinan, melainkan justru dapat mempertahankan kemiskinan mereka. Terkadang dicirikan sebagai “Negara Pengasuh” (Nanny State), para kritikus berargumentasi bahwa redistribusi (dalam bentuk pajak tinggi) dan subsidi menghilangkan kewirausahaan individu dan dengan demikian melemahkan pertumbuhan ekonomi. Jika seseorang selalu dapat bergantung pada negara untuk menjamin kesejahteraannya, apa insentif bagi mereka untuk berjuang dan membangun peruntungan mereka sendiri, dengan menggenggam nasib di tangan mereka sendiri?
Oleh sebab itu, telah muncul suatu “jalan ketiga” yang memfokuskan diri secara langsung pada upaya mempertahankan pertumbuhan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan kaum miskin melalu intervensi kebijakan eksplisit terhadap proses pertumbuhan – suatu “kebijakan pertumbuhan yang bersifat pro-poor”. Agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja bagi kaum miskin dan menghapus kemiskinan, ia harus dikombinasikan dengan perubahan distribusi yang radikal serta reformasi sosial. Yang lebih penting lagi, program-program anti-kemiskinan harus mempertimbangkan keadaan setempat, baik penciptaan lapangan kerja berbasis lokalitas maupun pengembangan kapasitas masyarakat. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pengentasan kemiskinan, reformasi sosial (termasuk program-program pemberdayaan dan perbaikan pendidikan dan kesehatan masyarakat) harus mendahului reformasi ekonomi. Pasar tidak dapat melakukan hal ini sendirian. Kita memerlukan legislasi negara, kepastian hukum dan nilai-nilai demokratis. Hal ini tidak akan mungkin tanpa kehadiran negara yang kuat yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk membatasi kekuasaan pasar dan mengalokasikan dana publik kepada kaum miskin. Sifat pro-poor adalah suatu pilihan dan desain yang bersifat politis dan ideologis yang melibatkan pengalokasian dana untuk keluarga-keluarga dan masyarakat miskin. Tidak semua orang akan mendukungnya, sebab itu artinya melakukan intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar dan mengambil uang dari orang kaya untuk mensubsidi orang miskin.
Kebijakan pertumbuhan pro-poor harus peka terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi dan secara aktif menangani ketidaksetaraan tersebut. Seringkali, kebijakan-kebijakan seperti ini mendukung pelayanan publik dasar: kesehatan, pendidikan, perumahan, air, sebab mereka secara eksplisit mentargetkan mereka yang tidak mampu membayar pelayanan swasta (di sektor swasta pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dan dikelola, tapi tidak harus disbusidi). Karena kemiskinan juga disebabkan oleh ekslusi, kebijakan pro-poor harus memungkinkan orang miskin dan keluarga-keluarga yang tidak beruntung untuk terlibat dalam pembuatan keputusan publik. Kebijakan pro-poor yang demikian ini diadopsi di dalam sepuluh hak dasar di dalam Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam dan lingkungan, keamanan manusia, dan partisipasi. Kebijakan pro-poor mencakup:
- Kebijakan redistributif seperti pajak progresif, subsidi dan land-reform
- Kebijakan tindakan afirmatif untuk menangani ketidaksetaraan sosial:
- Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah
- Akses pada kredit mikro yang murah (seperti Grameen Bank)
- Perencanaan dan penganggaran partisipatifyang berbasis luas dan difasilitasi, dimana kebutuhan orang miskin diprioritaskan, dengan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan bahwa target-target tercapai
- Anggaran berbasis kinerja yang berangkat dari program-program yang memiliki kegiatan dan indikator-indikator serta ukuran hasil yang teridentifikasi dengan jelas, yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok marjinal.
Perlu pula dicatat bahwa ada kebijakan pemerintah yang “netral”. Hal ini mencakup kebijakan pemerintahan umum yang melindungi semua warga negara, seperti perlindungan atas kebutuhan dasar manusia, penegakan negara hukum dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan yang netral seperti ini diperlukan tapi belum cukup untuk berfungsi sebagai prasyarat bagi kebijakan pro-poor. Ada pula kebijakan dan pengeluaran yang dianggap netral tetapi lebih menguntungkan mereka yang tidak miskin, seperti subsidi bahan bakar minyak (seorang pemilik mobil jeep yang haus bensin memperoleh subsidi lebih besar per bulannya daripada seorang pengendara motor). Dalam menganalisa kebijakan pemerintah dan strategi-strategi anti-kemiskinan, maka kita harus meneliti dengan seksama dokumen-dokumen dimana strategi-strategi tersebut diformulasikan.
Dan hal ini membawa kita pada topik utama buku yang sedang Anda pegang ini: penganggaran pro-poor. Mengapa penting memfokuskan diri pada anggaran? Sebab agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang konkrit, janji-janji, niat dan rencana perlu diubah menjadi anggaran. Salah satu definisi politik yang umum digunakan adalah “pengalokasian sumber-sumber daya yang jumlahnya terbatas di antara berbagai tuntutan yang saling bersaing.” Agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakannya, ia memerlukan dana. Sebab jika tidak, janji-janji indah para politisi akan tetap dalam bentuknya semula: yaitu janji. Karena dana terbatas, para pembuat kebijakan harus membuat keputusan untuk mengalokasikan dana di antara berbagai tuntutan yang saling bersaing. Produk akhir dari keputusan alokasi tersebut adalah anggaran. Dalam suatu anggaran lah kita dapat membaca niat para pembuat kebijakan serta cara-cara yang mereka usulkan untuk menangani kepedulian mereka.
Masalah di dalam anggaran adalah bahwa ia seringkali – dan ini bukanlah sesuatu yang khas Indonesia – kompleks dan sulit dibaca. Agar warga dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat membaca anggaran, mereka perlu bantuan. Dan di sinilah buku ini penting. Di dalam buku ini Anda akan belajar tentang apa itu kebijakan pro-poor dan bagaimana menganalisa anggaran yang ada untuk mengukur seberapa baik ia menerapkan berbagai kebijakan pro-poor dan pengentasan kemiskinan.
Buku ini terutama ditujukan untuk organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS). Peran warga dan OMS di dalam penganggaran paling sedikit ada dua. Yang pertama adalah terlibat di dalam penyusunan anggaran yang sesungguhnya. Di Indonesia, hal ini terjadi di dalam rapat-rapat Musrenbang di tingkat komunitas dan kabupaten/kota. Kedua, organisasi-organisasi masyarakat sipil harus pula meminta pertanggungjawaban pemerintah atas rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan mereka. Fungsi pengawasan yang terakhir ini perlu dilakukan baik di dalam persiapan dokumen-dokumen anggaran maupun dalam tahap pembelanjaan/ implementasi. Buku ini menyediakan pedoman tentang bagaimana Anda sebagai seorang warga negara dan sebagai aktivis kemasyarakatan dapar memainkan peran di dalam kedua fungsi tersebut dan memastikan bahwa dana publik dialokasikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Salah satu definisi penganggaran pro-poor adalah bahwa ia merupakan suatu cara sadar menangani ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalam proses penganggaran biasa. Suatu anggaran yang pro-poor dengan demikian peka terhadap berbagai perbedaan dalam hal sumber-sumber daya dan secara aktif menangani perbedaan tersebut. Dengan cara yang sama bahwa kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan bisa tidak peka terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, yang berujung pada penyerapan hasil akhir yang berbeda, anggaran pemerintah – meskipun dipandang “netral” – seringkali bias gender. Suatu anggaran pro-poor berupaya menangani konsekuensi negatif tersebut dan mengalokasikan dana publik kepada mereka yang memiliki sedikit pilihan pelayanan publik dan yang perlu dilindungi. Anggaran yang pro-poor dan sensitif gender dengan demikian adalah suatu alat untuk pengalokasian dana bagi orang miskin dan mereka yang paling membutuhkan. Ia adalah suatu proses dimana keluarga-keluarga miskin terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini membutuhkan upaya khusus dan tidak mudah dicapai, mengingat maraknya kekeluargaan dan penguasaan sumberdaya oleh kelompok elit. Contoh kebijakan yang pro-poor di antaranya:
- Dana umum yang dialokasikan untuk pelayanan dasar manusia dan infrstruktur publik, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan jalan-jalan pedesaan yang terutama akan menguntungkan orang miskin
- Alokasi anggaran untuk mensubsidi pelayanan publik (pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis)
- Alokasi anggaran yang sensitif gender untuk perempuan (seperti pelatihan bidan dan penyediaan tempat penitipan anak umum)
- Dana yang disisihkan untuk pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan seperti nelayan dan petani peladang kecil.
- Insentif finansial bagi perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan orang cacat, membangun pabrik di luar kota, atau melatih buruh-buruh kasar. – Dana darurat untuk penanganan bencana (pro-aktif, bukan post-facto.)
Seperti yang dicatat dengan benar oleh para penulis buku ini, suatu anggaran yang bersifat pro-poor adalah suatu pernyataan politik. Ia merupakan suatu dokumen ‘partisipatif demokratis’ yang mengirim pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah menganggap serius kemiskinan. Dalam membaca dan menganalisa suatu anggaran, kita dapat belajar tentang kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerjanya.
Anggaran yang bersifat pro-poor telah menjadi “rasa bulan ini”. Ada banyak manual pelatihan dan buku yang mengangkat topik ini, dan tampaknya lembaga-lembaga donor saling menginjak kaki satu sama lain untuk membuktikan diri sebagai donor yang paling peka terhadap gender dan perbedaan sosial lainnya (lihat Bab I buku ini untuk ulasan tentang hal ini). Bahkan pemerintah Indonesia merespon tantangan ini: MeNeg PP bekerjasama dengan Bappenas menyusun suatu inisiatif bagi anggaran yang responsif gender. Semua itu sangat baik – asalkan ia tidak sekedar menjadi mantra atau kotak yang harus diisi. Buku baru terbitan PraKarsa ini menambah nilai terbitan-terbitan lainnya, dalam arti bahwa ia menempatkan anggaran pro-poor dan anggaran responsif gender di dalam konteks politiknya: bagaimana kedua anggaran tersebut dapat dijadikan alat bagi suatu negara kesejahteraan untuk memperoleh tempat di Indonesia. Buku ini didasarkan pula pada pengalaman konkrit dari seluruh negeri selama dekade terakhir, dan dengan begitu merupakan suatu “buku sumber” bagi para aktivis kemasyarakatan dalam menganalisis dan mengadvokasi anggaran pro-poor. Karena itulah saya menganjurkan kepada semua pembaca untuk membaca buku ini dengan seksama dan memanfaatkan berbagai saran yang bermanfaat yang terkandung di dalamnya.



